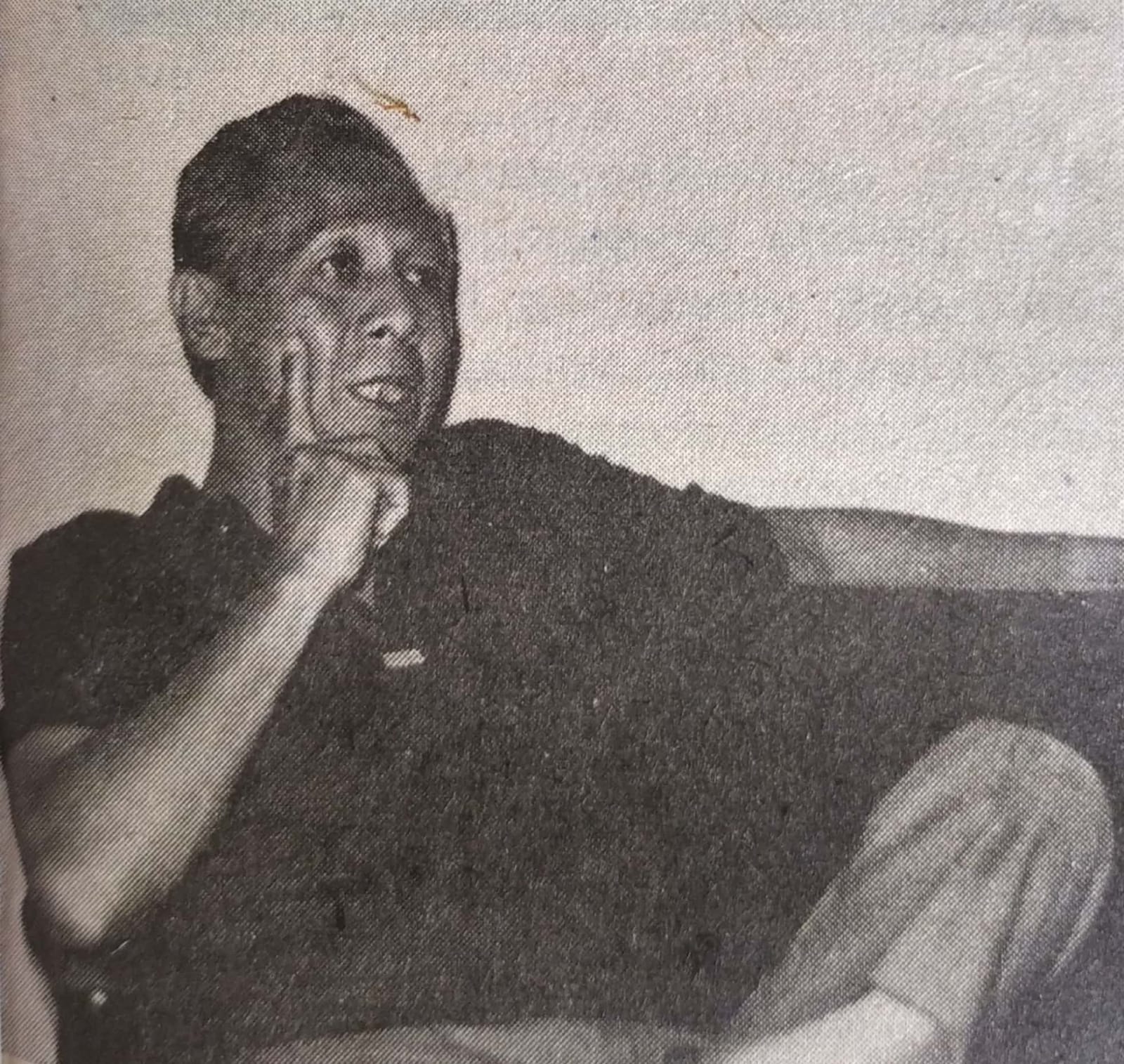
© Arsip/BAL
Gejolak transformasi peran pendidikan tinggi yang semula berfokus pada produksi pengetahuan menjadi penopang kebutuhan industri, muncul sebagai diskursus yang hangat beberapa tahun belakangan. Namun, orientasi ini rupanya telah mencuat jauh sebelum kebijakan manufakturisasi kurikulum, bahkan penetapan sejumlah perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara diberlakukan pada 1999. Melalui wawancara dengan BALAIRUNG, yang dimuat dalam rubrik Insan Wawasan Majalah BALAIRUNG No. 8/TH. II/1988, bekas Dekan Filsafat UGM, Koento Wibisono mengkritik paradigma perguruan tinggi sebagai pabrik penyedia kebutuhan pasar kerja, alih-alih tempat produksi pengetahuan. Berikut artikelnya.
Sayang, di UGM belum pernah ada pemilihan dosen berbusana terbaik. Andaikata ada, mungkin dia bisa menang, atau paling tidak masuk nominasi. Pakaiannya yang selalu rapi dan necis, kelihatan sebagai orang yang sangat formil. Tidak diketahui, apakah Dekan Fakultas Filsafat UGM yang selalu rapi ini ingin memberi contoh pada para mahasiswanya yang kebanyakan suka berpenampilan model seniman. Yang jelas, tampaknya ia lebih pas dengan penampilan seperti itu. Mengingat, sampai sekarang juga belum ada yang protes tentang penampilannya tersebut.
Pasangan yang baru dikaruniai cucu ini, mengaku menikah pada tahun 1957 saat mereka masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM. “Zaman itu biasa. Banyak teman-teman mahasiswa yang sudah menikah. Tapi kita juga sudah punya penghasilan. Di samping sebagai mahasiswa Ikatan Dinas saya juga mengajar di SMA Institut Indonesia”, kata Koento. Mereka bertemu pertama kali ketika masih sama-sama di SMA Negeri Solo.
“Ketika itu saya di bagian A, dia di bagian B”, cerita Bu Koento. Sayang, pertemuan ini kemudian dipisahkan oleh perang kemerdekaan kedua tahun 1948. Pemuda Koento harus bergabung dengan Tentara Pelajar di front pertempuran dan kemudian melanjutkan SMA-nya di Magelang. “Ketika pertama kali ketemu di Fisipol itu, dia langsung tertarik,” kenang Koento sambil melirik Bu Koento.
Entah ada hubungannya atau tidak dengan pernikahannya pada tahun 1957, yang jelas setelah pernikahannya itu ia lulus sebagai sarjana dan langsung mendampingi Notonagoro sebagai asistennya. Karena lebih banyak berkecimpung pada mata kuliah Filsafat, maka ketika tahun 1968 Fakultas Filsafat didirikan, ia langsung menjadi dosen di sana. Tahun 1969 mengikuti tugas belajar di Institut Tinggi Filsafat Leuven di Belgia, sampai tahun 1972. Tahun 1973 diangkat menjadi Pembantu Rektor III UGM sampai tahun 1979, ketika ia harus mengadakan penelitian di Belanda selama satu tahun, sekaligus juga mengajar mata kuliah Sejarah Filsafat Barat.
Sebagai persiapan final untuk promosi doktor, tahun 1982 kembali lagi ke Belanda beberapa bulan sampai akhirnya pada tahun yang sama ia selesai promosi doktor filsafatnya di UGM. Sejak itu, secara khusus ia mengajar Sejarah Filsafat Barat dan Filsafat Ilmu di samping juga Mata Kuliah Wajib Umum, Pancasila. Jabatan-jabatan yang sampai sekarang ia pegang adalah Dekan Fakultas Filsafat UGM sejak tahun 1984, anggota Dewan Riset Nasional sejak tahun 1985, Sekretaris Konsorsium Ilmu Sastra dan Filsafat sejak tahun 1985, Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) sejak November 1986. Di samping itu, ia juga masih harus mengajar S2 di UGM dan IAIN, juga sebagai dosen tamu di Lemhanas sejak tahun 1984.
Sebagai Rektor di UNS, yang ia inginkan adalah mengembangkan komunikasi secara terbuka di universitasnya itu. “Saya sendiri membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin bertemu dengan saya sepanjang saya ada di tempat,” katanya. Cita-citanya, ingin membawa UNS agar mahasiswanya terdiri dari setiap suku yang ada di Indonesia tanpa harus melanggar ketentuan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Berikut ini hasil wawancara Agung Suprihanto dengan Koento Wibisono di kediamannya, Bulaksumur D-17 dan di ruang kerja Rektor UNS, di Surakarta bulan Maret 1988.
Sekarang ini banyak anggapan bahwa kualitas mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi menurun. Bagaimana menurut Anda?
Anggapan itu adalah ya dan tidak. Ya dalam arti sistem pendidikan sekarang dihadapkan kepada segi kuantitas. Jumlah mahasiswa yang begitu banyak, memberikan implikasi mengalahkan kualitas. Ini pokok persoalannya. Dalam arti apa masalah kualitas itu? Yaitu sistem. Dulu pada zaman saya, sebelum masalah kuantitas ini muncul, para dosen bisa secara intensif menghadapi kelas yang kecil. Ujian tidak pernah tertulis, tapi lisan, sehingga seorang mahasiswa tidak pernah berani maju ujian kalau tidak belajar. Selama saya jadi mahasiswa hanya sekali ujian tertulis, yaitu pada kuliahnya Pak Notonagoro. Itu saja karena Pak Notonagoro sedang sakit-sakitan.
Pada ujian lisan, terasa sekali yang berani maju adalah mereka yang sudah benar-benar belajar dan belajar pun sesuai dengan buku referensi yang diwajibkan, sehingga segi kuantitas yang belum menjadi beban itu sangat bisa memperhatikan kualitasnya. Akibatnya, mereka yang lulus adalah mereka yang betul-betul sudah mendalami ilmunya dengan maksimal. Di samping itu, sadar akan kekurangannya, tahu segi mana yang harus ditambahkan sendiri, penguasaan bahasa, penguasaan literatur, dan sebagainya.
Bagaimana mungkin menguji satu persatu mahasiswa yang jumlahnya ratusan, sehingga sekarang dengan sistem semester itu sudah koden, siap atau tidak harus ikut ujian. Kalau perlu memakai sistem objektif tes, A-B-C-D itu. Inilah orang lalu menilai bahwa masalah kualitas menjadi terabaikan. Tapi juga tidak benar, sebab dalam setiap angkatan ternyata ditemukan bibit-bibit unggul.
Jadi, ukuran kuantitas dan kualitas itu tidak dapat digeneralisasikan. Kalau dikatakan kualitas menurun, ini ada benarnya, tapi tidak benarnya jangan dilupakan.

© Arsip/BAL
Dengan latar belakang kuantitas tadi, lalu upaya apa kira-kira yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi?
Nah, sudah sejak 2 tahun yang lampau, Fuad Hassan mengatakan, prioritas utama pengembangan ditekankan pada peningkatan kualitas pendidikan. Jalan yang ditempuh yaitu pertama, mengembangkan motivasi untuk sebanyak mungkin dosen mengikuti pendidikan formal Pascasarjana. Menteri mensinyalir bahwa ukuran dosen S-1 harus lulus S-2. Oleh karena itu, pemerintah pun mendapatkan pinjaman luar negeri guna memberikan fasilitas bagi program Pascasarjana.
Dalam hal ini, Universitas Gadjah Mada saya kira sangat beruntung. Kualifikasi dosen S-2 dan S-3 sudah bagus sekali. Bahkan yang terbagus, di samping IPB dan ITB. Dari sekian dosen yang ada, sudah lebih dari 50 persen yang bergelar master, doktor, dan sebagainya. Kedua, yaitu dengan peningkatan sarana akademik atau sarana pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, unit komputer, dan sebagainya.
Sebetulnya, ini boleh dibilang klise. Tetapi, harus diakui selain perangkat lunak, perangkat kerasnya juga merupakan faktor kunci. Kembali Universitas Gadjah Mada beruntung karena sarana pendidikannya sudah cukup lengkap. Ketiga, yakni merupakan simultan dari yang pertama dan kedua, yaitu peningkatan kegiatan akademik. Seminar ilmiah, simposium, rapat kerja, diskusi buku, penelitian, upgrading dosen, mengundang dosen luar negeri, dan sebagainya. Semua itu dikembangkan secara sadar terarah. Arahan Menteri ini diterjemahkan oleh pimpinan universitas di tempatnya masing-masing.
Rendahnya mutu lulusan perguruan tinggi, disinyalir juga karena kurang mampu berbahasa asing?
Saya juga merasakan hal itu. Kembali kepada sistem kita. Zaman saya dulu, sejak SD diajarkan baik bahasa Ibu maupun bahasa asing. Mengarang cerita, paramasastra atau gramatika diajarkan sedemikian rupa sehingga masalah bahasa merupakan masalah yang sangat diperhatikan.
Sekarang, saya tidak tahu mengapa menulis karangan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing tidak diajarkan. Sehingga, tidak hanya bahasa asing, bahasa Indonesia pun pada umumnya kita lemah. Padahal, bahasa itu adalah isi, manifestasi pengejawantahan seseorang untuk menerjemahkan pikirannya. Jadi, apabila penguasaan bahasanya tidak benar, ya apa yang ia bicarakan dan ia tulis ya tidak jelas.
Lalu, bagaimana dengan pengembangan kualitas lulusan universitas, khususnya dalam penanganan bahasa ini?
Masalah bahasa, menurut saya belum ditangani secara eksplisit, hanya secara periferi. Dalam kurikulum Pascasarjana dicoba dengan cara memberikan logika dan filsafat ilmu, sehingga minimal pikiran kita itu logis, walaupun dalam penerjemahan sangat terasa sekali kelemahan itu. Sekarang, belum ada cara menerobos agar kelemahan bahasa dapat diatasi. Pak Koesnadi pernah menganjurkan agar diadakan kursus cuma-cuma, tapi ya lagi-lagi mentalitas kita itu kalau belum butuh tidak berminat. Sudah butuh pun kadang-kadang tidak punya waktu.
Bagaimana dengan memperbanyak terjemahan?
Ya, bagus. Dana sudah mulai disediakan bagi universitas atau kegiatan untuk menerjemahkan buku-buku yang dibutuhkan. Tetapi, ini pun tidak 100 persen menolong, hanya membantu sifatnya.
Kalau demikian, apa yang paling bisa menolong?
Kalau saya boleh usul, adalah penyiapan secara dini. Sejak SD sudah diajarkan berbahasa Inggris di samping bahasa Indonesia. Kita tidak perlu saling menyalahkan, tapi sudah tiba saatnya bahwa penguasaan bahasa harus dikembangkan melalui kurikulum yang terprogram.
Apakah ini tidak menambah beban, sementara banyak kalangan menilai bahwa materi pelajaran dalam kurikulum saat ini sudah terlalu banyak?
Nah, ini gagasan Pak Fuad Hasan. Dalam berbagai kesempatan Pak Fuad menerangkan bahwa pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA akan dibakukan pada kurikulum inti. Misalnya, kurikulum inti itu sebesar 60 persen, artinya semua sekolah mengajarkan itu. Sisanya, sebesar 40 persen supaya diberikan muatan lokal, artinya kalau daerahnya pertanian, ya diberikan masalah-masalah pertanian, di daerah pesisir ya masalah kelautan, daerah dagang ya dagang dan seterusnya.
Ini konsep yang baru diujicobakan, sehingga pada saatnya nanti tercipta hasil pendidikan yang intelektualitasnya memadai karena memperoleh kurikulum inti, tetapi juga mudah memperoleh saluran kerja karena sudah tidak asing dengan environment atau lingkungannya.
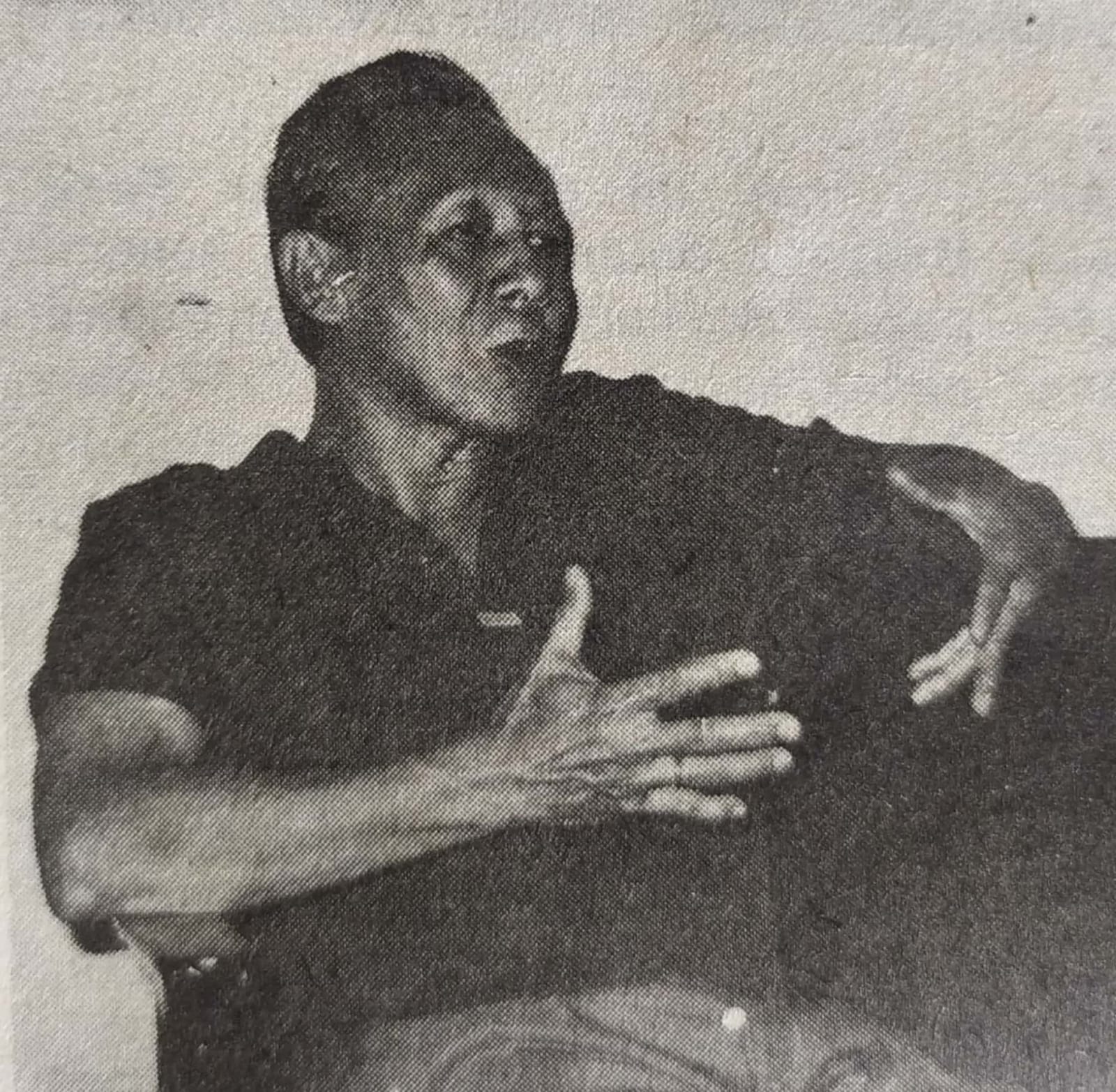
© Arsip/BAL
Kembali kepada lulusan perguruan tinggi, sekarang kita merasakan ketinggalan dengan negara maju, apalagi jika dikaitkan dengan banyaknya sarjana menganggur.
Nah, dalam hal ini saya selalu menekankan pada fungsi dan posisi Pendidikan Tinggi. Universitas bukan kursus, bukan akademi. Pengertian ini mohon ditanamkan. Universitas adalah lembaga pendidikan yang mempunyai peranan ganda. Peranan itu yaitu pertama, mempersiapkan masa depan, mempersiapkan penelitian, pemikir, orang-orang cendekiawan yang mampu tampil 10 atau 15 tahun yang akan datang, tidak harus melayani hari ini saja.
Dari sisi ini, universitas tidak jauh dari kepentingan kerja, tidak ada kaitannya dengan marketable job. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang. Pikiran orang cenderung pada peranan universitas yang kedua, yakni dapat bekerja dengan gaji tinggi. Seolah-olah universitas itu pabrik yang harus menjadi sambungan dari pemenuhan kebutuhan pasaran kerja. Sayangnya, pasaran kerja itu sifatnya teknis, relatif terbatas, sehingga oleh masyarakat lulusan universitas dituntut untuk segera terampil.
Padahal, seorang ahli tidak dapat langsung bekerja, ia memerlukan masa antara untuk menyesuaikan diri. Mengingat, orang lalu menyebutkan bahwa tugas universitas untuk jangka pendek itu harus mempersiapkan tenaga-tenaga yang trainable, teorinya kuat, tinggal dilatih 3 bulan menjadi ahli. itu yang dikatakan orang sekarang, universitas bukan akademi, bukan sekolah. Masyarakat tidak melihat kebutuhan 25 tahun yang akan datang, memerlukan pemikir, peneliti, orang yang memiliki daya abstraksi kuat.
Apakah masyarakat yang tidak tahu?
Nah, ini sering saya kemukakan. Masyarakat memandang ilmu pengetahuan hanya dari satu dimensi. Padahal, sebenarnya ilmu pengetahuan memiliki tiga dimensi. Masyarakat kampus seharusnya memiliki imperatif, memiliki kaidah hidup untuk mengabdi kepada ilmu, berpikir universal, tanpa pamrih dan skeptis, itu kaidah ilmu. Apa yang dipikir adalah hal-hal universal, apa yang dicapai adalah tanpa pamrih.
Dimensi pertama dari ilmu pengetahuan yaitu dimensi ilmu sebagai masyarakat. Ini sudah mentradisi sejak zaman Yunani kuno, abad tengah, dan zaman modern ini. Buktinya Jerman, Jerman boleh saja hancur karena kalah perang, tetapi karena tradisi ilmiah telah mereka miliki, dalam jangka waktu lima tahun mereka telah berhasil take off dan kembali makmur.
Di sisi lain, dimensi ilmu sebagai masyarakat ini, kita masih lemah dan belum pernah memiliki situasi yang kondusif. Kemudian, yang kedua adalah dimensi ilmu sebagai proses, yaitu masyarakat ilmiah yang merenung, mencoba, eksperimentasi, membandingkan, penelitian, penulisan buku, dan menemukan sesuatu.
Dimensi ketiga adalah dimensi ilmu sebagai produk, yaitu buku-buku, teknologi, teori orang lain. Nah, kita ini baru sampai taraf ini, yang kita ulet-ulet itu hanya ilmu sebagai produk. Teknologi dari luar, teorinya orang asing, komputer didatangkan, dan kita tidak pernah memikirkan. Persepsi kita sangat sempit, sehingga seperti yang Darmanto Yatman katakan, kita itu importir ilmu yang paling canggih.
Tetapi, mencontoh teorinya orang asing pun masih salah. Oleh karena itu, sistem S-2 dan S-3 itu dimaksudkan untuk membentuk suatu critical man, menjadikan masyarakat ilmiah. Jangan sampai dosen itu kumpul, urusannya hanya kredit rumah atau kredit eselon, tapi berpikir hal-hal yang universal, tanpa pamrih, menulis buku, dan sebagainya.
Lalu, terkait perangkapan dosen apabila dikaitkan dengan mutu lulusan perguruan tinggi itu bagaimana?
Saya kira, itu kondisi objektif yang tidak dapat terhindarkan. Terdapat dua pengertian di sini, yaitu merangkap di fakultasnya sendiri dan dalam arti dosen perguruan tinggi negeri mengajar di perguruan tinggi swasta. Hal yang pertama tersebut timbul karena kaderisasi yang kurang sempurna sehingga jarak dosen senior dengan dosen junior terlalu jauh. Guru besarnya sudah berusia cukup tua, sehingga untuk menyusul telah jauh. Akibatnya, harus membimbing atau merangkap.
Kedua, perangkapan dalam arti dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengajar di Perguruan Tinggi Swasta(PTS), ini harus dipandang dari segi positif, secara makro dan global. Kehadiran PTS harus, tidak bisa tidak. Conditio sine quanon, PTS merupakan jalan keluar bagi masyarakat yang haus pendidikan. Dalam hal ini, PTS berjasa, hanya dalam melakukan tugasnya ia kekurangan tenaga sehingga memerlukan bantuan dari PTN. Oleh karena itu, banyak dosen PTN yang terpaksa juga mengajar di PTS.
Lebih-lebih, kalau tenaga ini qualified, memiliki prestasi baik, kondisinya baik, tidak pernah bolos, memiliki ilmu yang tinggi, mentalitas yang menyenangkan, tentunya dosen tersebut akan sangat diperlukan. Masalahnya, saat ini jangan sampai perangkapan itu melebihi kemampuan rasional. Ini yang harus ditertibkan.
Sekarang terkait kemahasiswaan. Pada 1973-1979, Anda diangkat sebagai Pembantu Rektor III UGM, tentunya mengalami zaman-zaman NKK.
Sebenarnya, jauh lebih hebat lagi. Zaman Malari tahun 1974, kemudian lahirnya P-4, demonstrasi-demonstrasi tahun 1978. Ketika Daud Yusuf diangkat menjadi menteri, program NKK kemudian Dewan Mahasiswa di-pithesi satu per satu. Semua hal tersebut saya alami sebagai pembantunya Pak Sukadji (Rektor UGM saat itu).
Bagaimana kondisi kemahasiswaan saat itu apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini?
Kondisinya sangat berbeda, terutama kondisi politiknya. Pada waktu itu Orde Baru masih dalam taraf pencarian, mencari bentuk dan isi. Dalam upaya pencarian itu ditempuh tidak hanya melalui lembaga konstitusional, tetapi juga non-konstitusional seperti kampus. Ide, gagasan, dan konsep didukung oleh gerakan fisik berupa gerakan massa. Akibatnya, suka atau tidak mahasiswa harus terlibat di sini. Demonstrasi, turun ke jalan baik bagi yang mendukung konsep maupun yang melawan konsep.
Lain halnya dengan saat ini, Orde Baru telah menemukan bentuk dan isi yang lebih bagus sehingga kondisinya sangatlah berbeda. Dengan ditemukannya konsep tersebut, maka yang dikatakan aktivitas adalah aktivitas yang bersifat menjabarkan konsep tersebut. NKK saya kira adalah suatu jembatan untuk mengantarkan ke arah penemuan bentuk dan isis kehidupan kampus. Nah, kita sekarang tinggal menjabarkan.
Dibandingkan zaman sebelum NKK, untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, bagaimana dengan saat ini?
Dalam hal ini, saya mendukung pernyataan Pak Koesnadi, bahwa kehidupan kampus juga digunakan sebagai talent scouting bagi calon kepemimpinan. Sejarah telah membuktikan bahwa 70 persen atau 90 persen pemimpin nasional berasal dari dunia pendidikan. Para pemimpin nasional yang berasal dari latar belakang perguruan tinggi seperti Wahidin, Sutomo, Soekarno, Hatta, dan Syahrir, sedangkan para pemimpin nasional dari kampus seperti Sarwono, Akbar Tanjung, Cosmas Batubara, dan Nurcholish Madjid.
Semua ini isyarat bahwa perguruan tinggi harus menjadi wadah untuk mengadakan talent scouting dan memberikan bekal bagi para calon pemimpin nasional di masa depan. Di sini, sangat diperlukan upaya mengarahkan kegiatan sehingga para mahasiswa kaya akan konsep dan mampu menerjemahkan konsep itu dalam karya dan pendapat baik lisan maupun tertulis.
Untuk menghasilkan kepemimpinan itu, lebih bagus sekarang atau zaman-zaman sebelum NKK?
Tidak bisa dibandingkan, karena situasinya sangat berbeda. Talent scouting zaman Cosmas lahir dari jalanan dan demonstrasi. Masing-masing kondisi menuntut cara yang berbeda. Terlebih, sekarang kita telah mencanangkan kondisi yang stabil di negara kita. What every at means, suka atau tidak, yang dibutuhkan adalah kehadiran calon pemikir, profesional yang cakap dan memiliki tanggung jawab. [Agung]
Ditulis ulang dengan penyuntingan oleh Han Revanda Putra, Marshanda Farah Noviana, dan Naufal Ridhwan Aly.