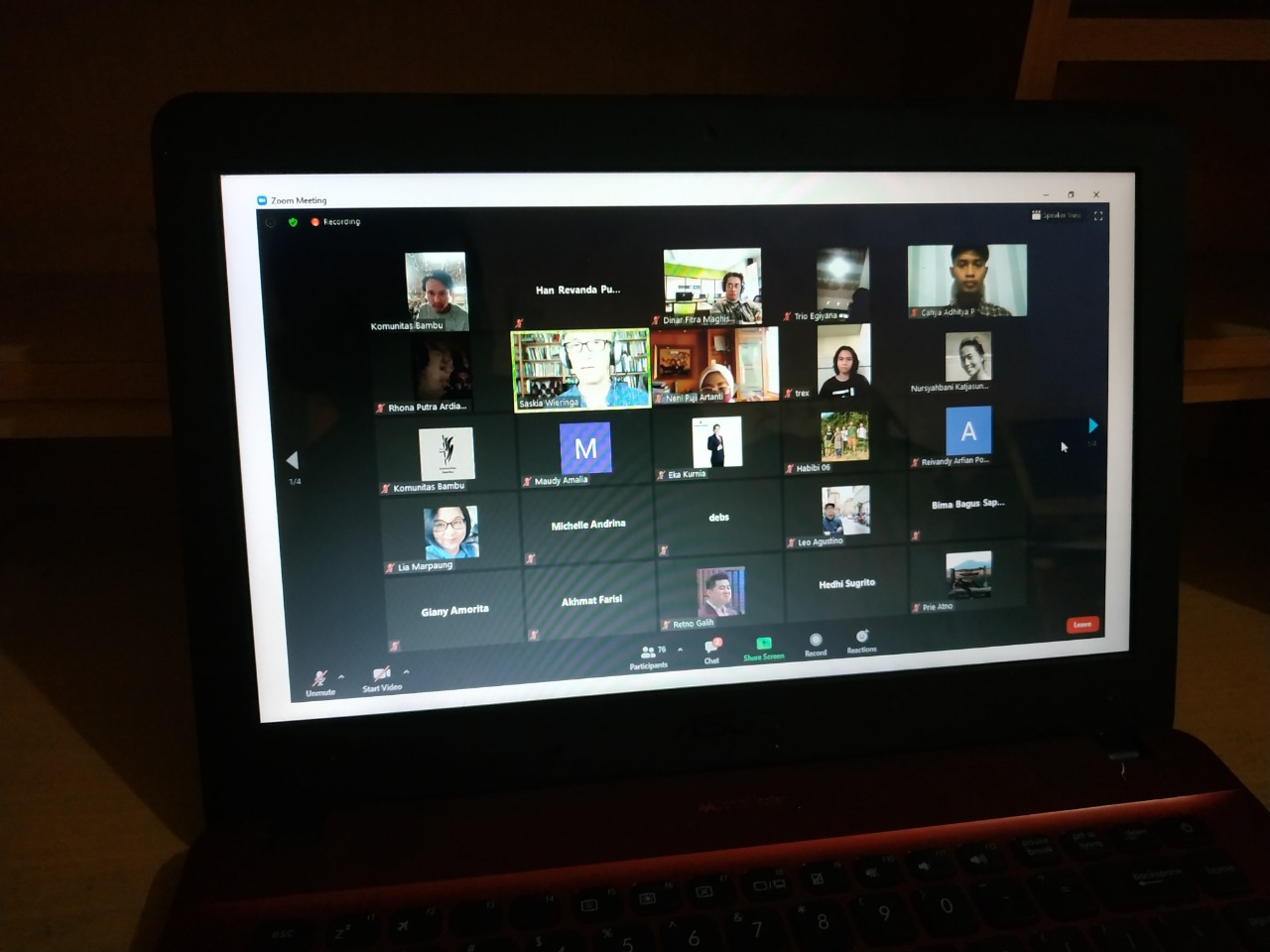
©Revan/Bal
Lebih dari lima puluh tahun hidup tanpa keadilan telah membuat sejumlah besar orang tertuduh simpatisan komunis terpinggirkan di tengah masyarakat Indonesia. Mereka dituduh secara sepihak terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tanpa melalui proses peradilan. Ironisnya, tanpa tahu seluk-beluk peristiwa tersebut, sampai hari ini mereka masih mendapat stigma atas kesalahan yang tak pernah mereka perbuat. Nasib lebih nahas dialami ratusan ribu orang yang dibantai secara massal dalam kurun 1965—66. Semua ini bermula dari propaganda yang dilancarkan secara meluas dan sistematis selama lebih dari tiga puluh tahun kekuasaan Orde Baru.
Untuk mengungkap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa itu, Saskia Wieringa dan Nursyahbani Katjasungkana telah memelopori Yayasan Indonesian People’s Tribunal 1965 pada Maret 2014 silam. Satu tahun kemudian, yayasan ini menginisiasi diadakannya pengadilan internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung sejak 1965. Salah satu temuan penting pengadilan tersebut yaitu adanya propaganda terhadap sejumlah besar orang yang dituduh berafiliasi dengan PKI serta terlibat G30S.
Berdasarkan temuan ini, Saskia dan Nursyahbani kemudian menulis buku berjudul Propaganda and Genocide in Indonesia: Imagined Evil. Komunitas Bambu, yang menerbitkan terjemahan atas buku ini dengan judul Propaganda dan Genosida di Indonesia: Sejarah Rekayasa Hantu 1965, mengadakan peluncuran sekaligus bedah buku ini pada Kamis (13-8). Dalam bedah buku tersebut, Saskia dan Nursyahbani hadir sebagai narasumber.
Saskia menjelaskan bahwa propaganda telah dilancarkan militer melalui dukungan CIA pasca-terjadinya peristiwa G30S. Selain mengklaim PKI sebagai dalang tunggal peristiwa tersebut, mereka juga menggambarkan komunis sebagai hantu atau biang kejahatan, seperti ateis, hiperseksual, amoral, dan pengkhianat bangsa. Menurutnya, propaganda ini telah memantik masyarakat sipil untuk turut melakukan pembunuhan massal dengan dalih “menyelamatkan NKRI”. Ironisnya, korban pembunuhan massal bukan saja anggota PKI, tetapi juga setiap orang terindikasi terkait partai tersebut, termasuk para pendukung Sukarno serta sejumlah korban salah tangkap. “Tanpa propaganda, pembunuhan massal tidak akan begitu massif,” jelasnya.
Propaganda juga meliputi sejumlah kebohongan terkait Gerwani, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI. Saskia menegaskan bahwa tarian “the scent of flowers” oleh para perempuan Gerwani dan penyiksaan serta pengebirian para jenderal adalah murni bohong. Namun, propaganda ini telah membuat sejumlah besar perempuan Gerwani diburu dan mengalami kekerasan seksual. “Mereka ditelanjangi untuk dicari cap Gerwani pada tubuh mereka, padahal itu tidak ada,” ujarnya.
Menurut Nursyahbandi, stigmatisasi juga berimbas represi terhadap para pengarang Lekra, organisasi kebudayaan yang berafiliasi dengan PKI. “Karya para pengarang Lekra cukup lama dilarang karena stigma,” jelasnya. Ia menyebut hal serupa terjadi pada lagu berjudul “Genjer-Genjer”, yang mengalami stigma sebagai “lagu PKI”. Padahal, lagu tersebut sudah dibuat sejak zaman Jepang tanpa intensi sebagai lagu komunis. Sepakat dengan Nursyahbandi, Saskia menyebut lagu ini sering dinyanyikan oleh ibu-ibu dan anak-anak petani ketika musim panen tiba. Anehnya, gerakan yang mereka lakukan dengan arit ketika sedang menyanyi dianggap sebagai latihan kekerasan.
Nursyahbandi menjelaskan bahwa propaganda ini berlangsung efektif karena dilakukan secara berulang-ulang. “Sesuatu yang dikatakan berulang-ulang akhirnya akan diyakini sebagai kebenaran,” ujarnya. Ironisnya, propaganda tersebut masih terjadi sampai hari ini, sehingga para penyintas belum bisa bebas dari diskriminasi dan stigma. Ia juga menyesalkan bahwa pemerintah sekarang tidak menghiraukan hasil IPT 1965, padahal menurutnya rekonsiliasi mungkin untuk dilakukan.
Saskia berharap buku ini akan memantik lebih banyak peneliti untuk mengungkap kebenaran seputar tragedi 1965. Menurutnya, hak asasi manusia akan sulit ditegakkan jika stigma ala Orde Baru masih langgeng dalam memori kolektif masyarakat. “Tanpa kebenaran, kita tidak akan maju,” tegasnya.
Penulis: Han Revanda Putra
Penyunting: Widya R. Salsabila