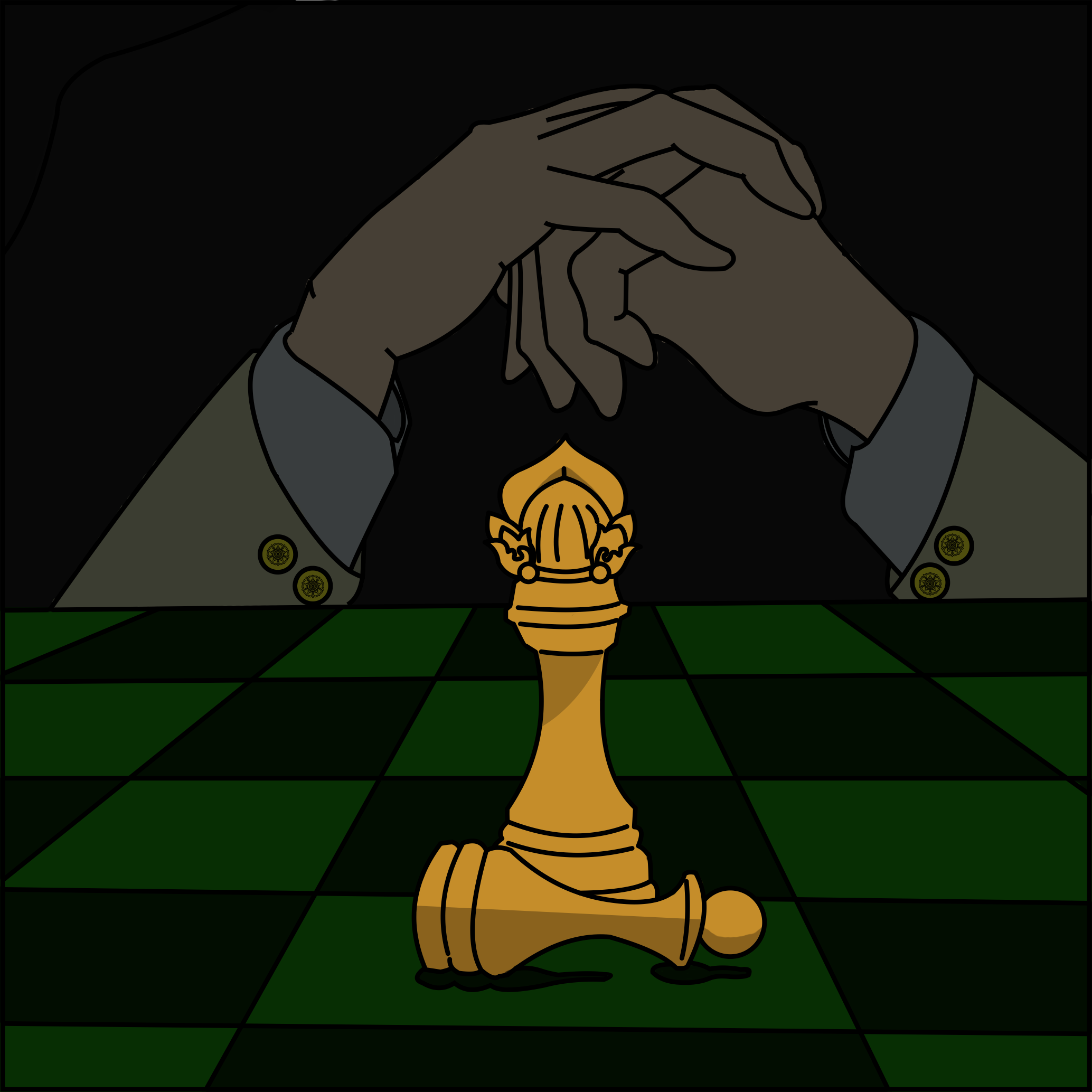“Adanya kecenderungan pemikiran konservatif di kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebabkan reforma agraria menjadi tabu untuk dibicarakan. Melihat UGM adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia, ini tentu dapat memengaruhi banyak pemikiran aktor-aktor lain.”
Kalimat itu diucapkan Barid Hardiyanto, S.Sos., M.Si., di tengah wawancara pada Rabu (21-02). Dalam kemelut konflik agraria yang banyak terjadi di Yogyakarta, Mahasiswa Doktoral Ilmu Administrasi Negara UGM ini menyatakan keresahannya terhadap potensi UGM menghambat reforma agraria. Dia menyatakan hal ini dengan melihat dua sisi fakta lapangan yang terjadi pada lingkungan akademisi UGM, yaitu adanya akademisi yang mempunyai pemikiran progresif dan konservatif. “Tentunya masih ada yang mempunyai pemikiran progresif terhadap pengupayaan masyarakat marginal,” jelasnya.
Reformasi atau reforma agraria merupakan upaya redistribusi dengan daya dukung seperti teknologi dan infrastruktur untuk mengatasi adanya ketimpangan struktur agraria. Struktur agraria yang dimaksud berupa bumi, air, udara, tata ruang, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh baik sebagian masyarakat maupun negara. Adanya reforma agraria bertujuan memenuhi hak-hak masyarakat terhadap penggunaan sumber daya alam yang dikuasai negara. Pemenuhan hak-hak ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang disokong dengan kekuatan modal dan infrastruktur.
Bila dikaitkan dengan persoalan tanah, reforma agraria disebut land reform. Land reform menurut Arif Novianto, asisten peneliti Master of Public Administration UGM, bisa diartikan tergantung pada konteks rezim yang berkuasa. Pada rezim Soekarno, land reform dilihat sebagai upaya redistribusi tanah. Petani dan buruh kecil diharuskan mempunyai minimal dua hektar tanah untuk diolah. Di sisi lain, orang-orang kaya yang mempunyai lahan lebih dari dua puluh hektar harus memberikan tanahnya kepada petani dan buruh kecil. Berbeda dengan Soekarno, Soeharto lebih memilih untuk tidak mempermasalahkan struktur penguasaan tanah dan ketimpangan lainnya. Keputusan Soeharto tersebut diimplementasikan dengan realisasi Revolusi Hijau yang berfokus pada peningkatan input-input teknologi pertanian. Kemudian, pada rezim Jokowi, land reform dilaksanakan dalam wujud sertifikasi tanah. “Meskipun konteks land reform berbeda setiap rezimnya, tujuan utama land reform adalah sama yaitu mengupayakan solusi ketimpangan agraria,” tuturnya.
Reforma agraria sejatinya telah berkembang dari zaman pasca-revolusi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Menurut Arif, Undang-Undang Pokok Agraria 1960 memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu hak kepemilikan tanah yang tidak boleh bersifat komunal. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 hanya mengakui hak-hak privat dan hak-hak milik pribadi atau keluarga. Sebuah kelompok masyarakat tidak boleh memiliki seratus hektar tanah secara bersama. Bukti nyata hal tersebut adalah penguasaan tanah yang terjadi di Riau tahun 2016. Saat itu, Wilmar Group menguasai hampir satu juta hektar tanah sedangkan masyarakat sekitarnya tidak memiliki satupun hektar tanah. “Padahal konflik penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat timpang sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan sertifikasi tanah,” jelas Arif.
Bicara tentang konflik agraria, Arif bertutur bahwa ketimpangan dalam konteks umum diukur dari Indeks Gini yang dapat dilihat pada setiap rezim. Semakin miring indeks yang didapat, semakin timpang agrarianya, di mana pada saat ini rasionya lebih besar dibanding saat orde baru. Tidak hanya itu, ia menambahkan, ketimpangan yang sekarang terjadi terlihat pada hegemoni penguasaan tanah oleh pemerintah dan perusahaan. Mengamini pernyataan Arif, Barid mencontohkan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Seperti 85% hutan di Jawa yang dikuasai Perhutani sedangkan di pinggiran hutan terdapat sekitar enam ribu penduduk yang miskin. Selain itu, ketimpangan juga terjadi di daerah Darmakradenan. Sebanyak 30% lahan mereka dikuasai oleh PT. RSA dan 40% dikuasai oleh Perhutani, sedangkan masyarakat hanya menguasai kira-kira 1/3 dari lahan yang ada.
Pemberlakuan Undang-Undang Keistimewaan menjadi satu contoh ketimpangan agraria di Yogyakarta. Pada awalnya, dalam menerapkan reforma agraria, Yogyakarta mengacu pada undang-undang pusat yaitu Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Namun, Yogyakarta diberikan wewenang Undang-Undang Keistimewaan pasca-reformasi yang melegalkan Pakualaman Ground (PAG) dan Sultan Ground (SG). Dilegalkannya PAG dan SG ini menyebabkan maraknya pengklaiman tanah masyarakat secara sepihak oleh keraton. Hal ini terjadi karena data posisi dan luas tanah kepemilikan Sultan masih belum ada dan belum terverifikasi. Pengakuan secara sepihak ini hanya mengandalkan narasi dan klaim bahwa tanah itu adalah milik Sultan.
Adanya klaim PAG atau SG juga berpengaruh terhadap kontribusi akademisi UGM dalam mewujudkan reforma agraria. “Kalau bicara soal PAG atau SG, UGM dipandang tidak berani bersuara karena UGM tidak berdiri pada tanahnya sendiri, melainkan pada tanah Sultan,” jelas Arif. Padahal, menurutnya, kontribusi akademisi UGM dalam konteks kampus kerakyatan adalah berani bersikap. Sebagai intelektual, para akademisi harusnya menjadi teman atau sahabat yang menyuarakan dan memperjuangkan masyarakat.
Selaras dengan Arif, Barid menyatakan satu aspek yang fundamental terhadap kontribusi akademisi UGM pada reforma agraria. “Terjadi kecenderungan pemikiran konservatif atau perspektif pasar di kalangan akademisi UGM sehingga terdapat potensi menghambat reforma agraria,” ungkapnya. Pemikiran konservatif yang dimaksud adalah pemikiran yang berpihak pada pemerintah dan kepentingan bisnis. Hal ini berpengaruh besar karena akademisi dipandang sebagai aktor yang berperan penting dalam proses reforma agraria.
Akan tetapi, Barid tidak serta merta mengatakan seluruh akademisi UGM terlibat dalam menghambat reforma agraria, karena masih ada akademisi UGM yang mempunyai pemikiran progresif, yaitu pro rakyat. Arif juga mengatakan kurang tepat jika melihat sisi UGM secara institusional. Menurutnya, individu yang mengatasnamakan UGM dalam keterlibatannya di beberapa proyek tidak mewakili institusi secara menyeluruh. Jadi, konteks UGM menghambat reforma agraria hanya dilihat pada aktor yang terlibat proyek, bukan semua individu di dalamnya maupun sebagai institusi.
Walaupun tidak ada aturan tertulis mengenai pelarangan kelompok atau individu UGM untuk ikut andil dalam proyek luar, Arif menjelaskan tetap ada kode etik di dalamnya. Kode etik yang dimaksud berupa visi dan identitas UGM sebagai kampus kerakyatan yang memihak rakyat kecil. Hal tersebut mengikat akademisi UGM dalam mengambil proyek di luar lingkungan pendidikan. Jadi jika proyek yang dijalani baik secara individu maupun kelompok merugikan rakyat kecil, maka akan bertolak belakang dengan visi dan identitas UGM. Jika dilihat lebih luas mengenai apakah pantas seorang akademisi bekerja dalam proyek di luar lingkup akademis, Arif menjelaskan hal itu tergantung budaya yang berkembang di lingkungan kampus. ”Kalau UGM memang benar-benar ingin memegang budaya kampus kerakyatan, mengambil proyek yang merugikan rakyat kecil secara kode etik adalah salah,” tuturnya.
Permasalahan lain adalah terjadinya liberalisasi keikutsertaan akademisi UGM dalam proyek yang mendikte arah penelitian. Seperti yang terjadi pada korban penggusuran tanah restorasi gumuk pasir di Parangkusumo yang meminta tanggung jawab doktor-doktor UGM. Mereka dianggap terlibat kerjasama menggusur tanah warga.[1] Tak hanya itu, terjadi juga skandal dosen geografi dan kehutanan UGM yang memberikan kesaksian palsu mengenai gugatan pabrik semen di Kendeng tanpa melakukan penelitian lapangan. Dosen tersebut cenderung membela perusahaan yang menaungi penambangan. Padahal, akademisi UGM sebagai intelektual harus mempunyai tanggung jawab sosial sebagai pembela masyarakat. “Jika keberpihakan dan tanggung jawab sosial akademisi UGM lemah, maka akan cenderung mudah menerima tawaran pengerjaan proyek manapun,” tambah Arif.
Barid juga menambahkan bahwa keterlibatan akademisi UGM dilihat dari aspek ekonomi politik. Kepentingan ekonomi politik berpengaruh ketika tanah UGM yang disewa oleh perusahaan ternyata menimbulkan konflik di masyarakat. Dia mencontohkan konflik petani teh Pagilaran meminta 800 hektar perkebunan yang dikuasai oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM sejak 1964.[2] Para petani mengaku terhimpit dengan perolehan upah yang minimum. “Jika UGM mempunyai budaya pemikiran progresif, tentu kepentingan ekonomi politik bisa terhindar,” ungkapnya.
Barid berharap akademisi UGM banyak menilik kehidupan masyarakat, mulai dari turun ke lapangan hingga tinggal di tengah masyarakat. Selain itu, Barid juga berharap akademisi UGM banyak memunculkan riset-riset ilmiah yang dapat memberi jalan keluar untuk perbaikan masyarakat. Demikian juga Arif, dia berharap daftar hitam akademisi yang terlibat skandal proyek bisa digagas. Hal ini akan menyebabkan mereka berpikir ulang dan mempertimbangkan tata nilai yang sudah UGM bangun sebagai kampus kerakyatan. “Kita harus mengembalikan UGM pada arahnya, jangan biarkan orang-orang yang terlibat skandal proyek membawa UGM ke arah yang berlawanan,” tutup Arif.
[1] Lihat di Rumah Baca Komunitas, “Mengurai Konflik Agraria di Jogja”,
www.rumahbacakomunitas.org/mengurai-konflik-agraria-di-jogja
[2] Lihat di Liputan6, “Ribuan Petani Teh Pagilaran Menyerbu Kampus UGM”,
www.liputan6.com/news/read/50268/ribuan-petani-teh-pagilaran-menyerbu-kampus-ugm
Penulis: Andara Rose K, Vania Rebecca
Editor: Bening Anggani