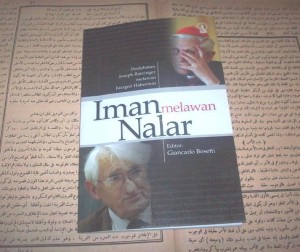
Judul buku : Iman Melawan Nalar
Editor : Giancarlo Bosetti
Penerbit : Kanisius, Yogyakarta
Penyadur : Hary Susanto SJ
Cetakan : I, 2009
Halaman : 87 halaman
Ilmu pengetahuan hanya dapat diciptakan oleh mereka yang dipenuhi gairah untuk mencapai kebenaran dan pemahaman. Tetapi, sumber perasaan itu berasal dari tataran agama… Saya tidak dapat membayangkan ada ilmuwan sejati yang tidak mempunyai keimanan yang mendalam seperti itu…
(Albert Einstein, 1939)
Sekalipun sudah ribuan kali dikutip, pidato ilmuwan paling jenius abad ke-20 itu hingga hari ini masih terlihat gagah. Bagian yang paling diingat orang dalam pidato di depan Princeton Theological Seminary itu berbunyi: ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta.
Hidup semasa dengan Einstein, seorang pendeta Jesuit dan pakar palaentologi bernama Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Ia mengkritik ortodoksi agama sama kerasnya ketika ia mengkritik kepongahan sains. Sumber kebenaran mestinya dicari di dunia materi, bukan dimagisterium gereja. Demikian sikapnya dihadapan para teolog. Sementara di depan ilmuwan, ia menelanjangi sains yang telah menjelma “worship of matter” atau penyembahan kepada materi (Rakhmat, 2003).
Akan tetapi, Einstein dan de Chardin adalah perkecualian. Tak banyak orang yang bisa menyerasikan kejeniusan dan spiritualitas secara berbarengan. Keduanya adalah sosok yang melambangkan integrasi ketika iman dan nalar berada dalam perjumpaan yang saling mengisi dan memperkaya.
Sebelum itu, juga sampai sekarang, hubungan antara iman dan nalar lebih sering diisi kepahitan dan pertengkaran. William A. Wallace dalam Religion and Science: Must There be Conflict (2003) merawikan beberapa perdebatan yang tegang dan saling menyerang antara nalar dan iman. Tahun 1615, misalnya, Galileo terpaksa dipecundangi Bellarmine. Galileo berkeras antara kitab alam dan kitab tertulis sama-sama dikarang Tuhan, sehingga tak mungkin ada perbedaan. “Tafsirkan kembali firman dalam kitab suci sehingga sesuai dengan temuan ilmiahku!” Seru Galileo. Dengan mudah Bellarmine membalas, “prinsipmu bagus dan alasanmu kuat, tapi apa kamu sungguh menemukan apa yang kamu kira sudah kamu temukan? Jika bisa didemonstrasikan, yakinkan sesama ilmuwan…jika tidak, serahkan saja Alkitab pada para ahli Alkitab…” Bellarmine pun menang. Galileo akhirnya menghadapi inkuisisi gereja tahun 1633. Inilah momen saat nalar takluk di depan pengadilan agama.
Yang terjadi tahun 1859 adalah sebaliknya. Debat antara Huxley dan Wilberforce dikenang sebagai momen kemenangan sains. Huxley mewakili evolusionisme Darwinian, Uskup Wilburfoce mewakili ortodoksi gereja. “Dari mana asal monyet, dari pihak kakekmu atau nenekmu?” serang Wilberforce dengan retorika argumentum ad hominem. Huxley cepat membalas, “lebih baik aku keturunan monyet daripada keturunan uskup!” Cepat-cepat ia menambahkan, “Seandainya ada nenek moyang yang aku malu mengingatnya, ialah orang yang akalnya gelisah dan luas, yang karena tidak puas dengan keberhasilan dalam aktivitasnya, ia menceburkan diri pada masalah ilmiah yang tidak ia ketahui sama sekali, hanya untuk memperkeruhnya dengan retorika tanpa arah…dengan menggunakan acuan prasangka keberagamaan.” Pada momen ini, nalar menang dan agama tumbang.
Kita bisa menghabiskan ribuan halaman untuk mencatat kronik dan menganalisis relasi antara keduanya di sepanjang masa. Buku berjudul Iman Melawan Nalar ini adalah satu di antaranya: merekam perdebatan yang berlangsung Januari 2004 lalu antara Jürgen Habermas dan Joseph Ratzinger yang kini menjadi Paus Benediktus. Yang dibahas bukan lagi soal kitab suci dan sains, tapi relasi iman dan nalar dalam kehidupan bersama.
Konteks yang memungkinkan kita untuk memahami perdebatan ini adalah sejumlah kenyataan global yang terjadi dewasa ini. Kian terlihat bahwa baik nalar dan iman mengalami absolutisasi dan masing-masing mengambil jalan sendiri. Kesenjangan tata ekonomi global dan tragedi 11 September adalah contoh baik untuk menjelaskan bahwa absolutisme nalar dan iman ternyata berbahaya buat nasib kemanusiaan.
Sejak kurang lebih dua setengah abad silam, di Eropa, dengan ditopang filsafat dan sains, nalar menempati keleluasaan ruang publik. Sementara iman atau agama dikurung dalam ruang privat. Itulah sekularisasi, upaya pemisahan antara “dunia sini” dan “dunia sana”. Memang, menurut Budi Hardiman (2007), sekularisasi mesti diingat sebagai prestasi Eropa dalam usahanya untuk membebaskan diri dari absolutisme agama yang saat itu memegang otoritas politis terlampau besar. Absolutisme agama adalah patologi lantaran setiap tata aturan disakralisasi. Tentu persoalannya tidak terletak pada agama, melainkan pada klaim pemuka agama yang atas nama Allah menunggalkan interpretasi terhadap kebenaran.
Sekularisasi menjadi jalan baru bagi masyarakat Eropa untuk hidup dalam terang akal. Namun, sekularisme juga mengandung patologinya sendiri. Dengan alasan pluralitas, negara sebagai lembaga yang mengatur kehidupan bersama ingin menjaga netralitas terhadap pelbagai nilai yang ada. Akan tetapi, hal itu seringkali dilakukan dengan menyingkirkan alasan-alasan relijius. Dari sisi ini, berbagai tindak onar atas nama agama yang dilakukan di luar kemapanan sistem tidak layak disalahkan begitu saja. Secara filosofis, itu terjadi lantaran iman atau agama tidak dimungkinkan untuk ikut serta dan berkontribusi dalam ruang publik. Ide tentang negara sekular layak diperdebatkan kembali karena agama tidak lumpuh dan punah begitu saja. Di level individu, agama justru semakin kuat, dikenal, dan merasuk walaupun secara institusional memang melemah.
Perdebatan dua tokoh ini dengan sendirinya merefleksikan nalar dan iman yang duduk dalam satu meja dan saling bertegur sapa. Habermas, kita tahu, adalah filsuf mazhab Frankfurt yang sepenuhnya mengimani rasionalitas. Habermas masyhur dengan teori deliberasi, rasio komunikasi dan ruang publik yang bernaung dalam rumpun teori kritis. Sementara Ratzinger dikenal sebagai pribadi yang teguh menjaga ortodoksi Katolik. Ia, kini, di hadapan umat Katolik tak mungkin “salah” karena memegang otoritas tertinggi gereja yang sepenuhnya berpegang pada kebenaran transenden.
Baik Ratzinger maupun Habermas dalam perdebatan ini sama-sama memakai istilah paska sekular. Relevansi istilah ini adalah potensinya untuk menjadi semacam “medan bersama” ataucommon ground bagi proses dialog antara iman dan nalar. Secara historis, paska sekular mau menjelasan ciri zaman dimana tradisi relijius dan komunitas iman mengalami suatu titik balik karena kejadian politis di tahun 1989, yakni momen peruntuhan Tembok Berlin. Secara teoritis, istilah ini mau menyatakan bahwa nalar dan iman perlu memerhatikan secara sungguh-sungguh sumbangan yang diberikan masing-masing pihak. Paska sekular adalah dimensi kehidupan sosial dan kultural yang secara serius berusaha menerjemahkan dan memahami bahasa relijius dan non-relijius secara timbal balik.
Mereka yang tekun menyimak perkembangan teori kritis akan segera melihat bahwa yang khas dari Habermas dalam debat ini adalah penggunaan dan penekanan public use of reason dalam proses komunikasi publik. Habermas mengawali argumentasinya pada teori liberalisme politik dari Kant. Liberalisme politik adalah legitimasi non-relijius dan legitimasi paska metafisik yang menjadi dasar normatif pembentukan negara demokratis konstitusional. Liberalisme penting artinya bagi pluralisme sebagai fakta kemasyarakatan yang tak terbantah.
Dalam isu pluralisme, Habermas lalu mengolah kembali teori Rawls tentang keadilan hingga formulasi liberalisme politis. Dalam titik ini, sebagaimana ideologi-ideologi lain, agama memiliki hak dan peran politis. Agama baru bisa bicara pada ruang publik selama patuh pada “klausul kondisional”, yakni agama mesti berbicara dan merepresentasikan diri dalam rasionalitas publik. Agama(wan) mesti mengoperasikan gagasan dan aspirasi relijius melalui rasionalitas publik tanpa harus mengorbankan pluralisme. Habermas melihat eksistensi agama dalam masyarakat sekular sebagai fakta yang tak melulu sosial. Karenanya ia menyeru, “filsafat harus memikirkan secara serius fenomen ini sebagai sebuah tantangan kognitif.”
Sedang Ratzinger mengawali uraiannya dengan meninjau kenyataan masyarakat global yang makin terhubung satu sama lain. Di sana terjadi proses saling memengaruhi yang cenderung mengikis kontrol moral dan yuridis. Pendeknya, apa yang disebut etika menjadi semakin tak bermakna dalam masyarakat global. Situasi ini meliarkan potensi mencipta dan merusak di antara manusia dan dunia yang dihuninya. Ratzinger melihat ilmu pengetahuan semakin mustahil diharapkan mampu melahirkan etika.
Ratzinger juga mempersoalkan kebenaran yang diperoleh negara sekular melalui logika representasi. Kebenaran lalu selalu ditentukan oleh mayoritas. “Masalahnya,” kata Ratzinger, “mayoritas pun dapat menjadi sempit, buta, dan tidak adil.” Pengalaman sejarah berkali-kali membuktikan hal itu. Di sisi lain, Ratzinger menyadari bahwa fanatisme relijius amat riskan. Fanatisme bukannya mewujudkan misi penyelematan atau penyembuhan tapi bisa berujung pada terorisme. Ia meyakini pentingnya kesediaan timbal balik untuk belajar. Patologi agama perlu “memandang cahaya ilahi nalar sebagai pengontrolnya”. Patologi hybris (kesombongan) yang diidap oleh nalar pun mesti “mengakui batas-batasnya” sembari belajar memahami keagungan tradisi relijius agar nalar tak menjadi “kekuatan yang menghancurkan”.
Habermas dan Ratzinger memakai pisau bedah yang berbeda: filsafat dan teologi. Keduanya sama-sama kukuh, namun tanpa prasangka dan hasrat untuk menjatuhkan. Nuansa dialektis untuk mencari “sintesis yang mungkin” sangat terasa dalam debat ini.
Mau tak mau, selesai membaca buku kecil nan bergizi ini, saya teringat Indonesia yang, tentu saja, bukan Eropa. Kita tahu ada kontroversi RUU semacam Sisdiknas, KUB, hingga APP. Teringat pula polemik “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta hingga kecenderungan formalisasi syariah sebagai perda. Sebagai sebuah pengalaman berbangsa dan bernegara, ternyata agama mampu melibatkan dirinya secara formal. Namun, ketimbang menilai, barangkali lebih bijak untuk bertanya, “seberapa sungguhkah ikhitar kita sebagai masyarakat majemuk melangsungkan dialog antara agama dan kepentingan publik secara setara dan rasional? Seberapa mungkin agama(wan) mesti membahasakan sisi epistemik keyakinan relijius sebagaimana publik mesti belajar memahami agama lebih dari sekadar persoalan individu dan fakta sosial?”
Berat, tapi pemahaman dan pengalaman kita pula yang bakal menjawabnya. WaLlahu A’lam[Ofa]
1 komentar
Berikan secara lengkap biodata penulis dari buku yang berjudul iman melawan nalar