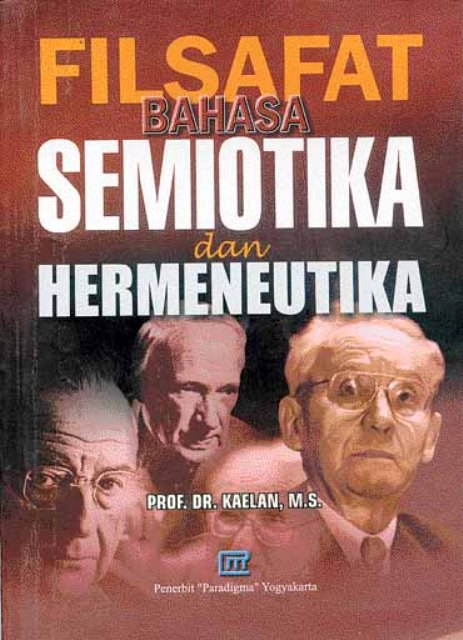
istimewa
Ada peribahasa melayu terkenal yang berbunyi “bahasa menunjukkan bangsa“. Peribahasa ini merujuk pada pemahaman mengenai identitas. Usaha-usaha penilaian asal-usul ataupun latar belakang kehidupan seseorang dari bahasa yang digunakannya, yaitu pemilihan diksi serta gaya intonasi tutur kata. ‘Bangsa’ disini bukan berarti ‘bangsa’ dalam istilah populer yang biasa kita gunakan sekarang, seperti misal penyebutan ‘Bangsa Indonesia’. Kata ‘bangsa’ dalam peribahasa ini mengarah pada pemahaman masyarakat melayu ketika itu, yang mengartikannya sebagai ‘bangsawan’, orang-orang yang dianggap berada di golongan atas. Bisa jadi raja, putra-putri kaum ningrat, maupun ulama yang stara sosialnya dianggap lebih tinggi daripada petani ataupun rakyat biasa.
Berbeda dengan zaman melayu kuno, kali ini giliran modernisasi dan demokrasi. Kasta ataupun strata sosial seperti bangsawan sudah sangat berkurang maknanya. Namun, bahasa masih berarti identitas, suatu simbol yang menunjukkan komunitas dan kapasitas seorang individu. Misal, ulama dan presiden, harus betul-betul memilah hati-hati tutur katanya agar dapat didengar baik oleh masyarakat. Bahasa tetap memiliki nilai konsekuensi dalam tiap penggunaannya.
Dalam bukunya yang berjudul Filsafat Bahasa, Prof. Dr. Kaelan, M.S. menuliskan tentang pengertian bahasa yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem simbol. Bahasa bukan hanya urutan bunyi-bunyi secara empiris, namun juga memiliki makna yang nonempiris. Dengan demikian, bahasa merupakan sistem simbol yang memiliki makna, juga sebagai alat komunikasi manusia, penuangan emosi manusia, serta merupakan sarana pengejawantahan pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mencari hakikat kebenaran hidupnya.
Menggarisbawahi penjelasan Kaelan, bahasa sungguh lekat dalam kehidupan sehari-hari seorang individu. Dengan begitu, individu tersebut juga meneguhkan eksistensi identitasnya dalam kebahasaannya. Saya misalnya, tinggal dan bersosialisasi dalam lingkungan yang memiliki bahasa berbeda dengan bahasa yang saya mengerti sejak kecil. Saya tinggal dan berkuliah di Yogyakarta, dimana mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Jawa.
Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari ini bukan perkara sepele. Awalnya hanya persoalan kecil, seperti ketidakpahaman saya waktu membeli makanan ataupun ketika berada di tempat umum lainnya, itu pun hanya berlangsung sebentar pada bulan-bulan pertama saya di kota ini. Namun semakin bertambahnya individu dan komunitas yang perlu saya hadapi, membuat saya semakin resah. Terkadang dalam suatu perbincangan dengan empat atau lima orang teman yang berbahasa Jawa, hanya saya yang tidak mengerti dan menjadi invisible girlketika mereka tertawa terbahak-bahak dengan guyonan Jawa-nya.
Saya juga terkadang ditertawakan karena tidak mengerti pisuhan berbahasa Jawa. Sepertijancuk, asu, dan lainnya. Buat saya memang tidak kasar, diucap ribuan kali pun tidak akan sampai makna ‘kasar’ dari kata-kata tersebut. Ini karena saya tidak terbiasa dan tidak terlalu peduli dengan arti kata tersebut. Meski begitu, secara tidak langsung saya pun membiasakan diri. Kerap kali saya ikut-ikutan bercanda dengan memanggil teman dengan akhiran cukseperti yang dilakukan teman yang lainnya. Namun buat saya kata cuk itu tetap tidak punya arti khusus. Hanya berupa bunyi dengan tiga huruf, c-u-k. Selesai.
Kembali pada pemahaman bahasa menunjukkan bangsa, dimana kata-kata yang diucapkan menunjukkan suatu golongan atau komunitas yang bersangkutan. Eric Fromm (1947) mejelaskan, identitas diri dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial seseorang dalam konteks komunitasnya. Identitas diri tidak dapat dilepaskan dari norma yang mengikat semua warga masyarakat tempat ia hidup dan peran sosial yang diembannya dalam masyarakat. Dengan begitu, ternyata cuk yang saya ucapkan bukan hanya sekedar bunyi yang keluar karena pelafalan tiga kata itu. Kata cuk yang saya ucapkan merupakan bentuk komunikasi saya yang keluar secara sadar. Yaitu suatu upaya ekspresi ketertarikan untuk dapat juga berbaur dengan komunitas.
Dengan begitu, walaupun secara maknawi saya memiliki kata cuk yang berbeda, saya tetap ingin dianggap sebagai bagian dari komunitas yang saya tinggali. Komunitas yang seringnya, berbahasa Jawa yang sebagian besar kata-katanya tidak saya pahami. Ternyata bukan hanya bahasa secara umum, tapi pisuhan juga dapat menunjukkan bangsa. [Afra]