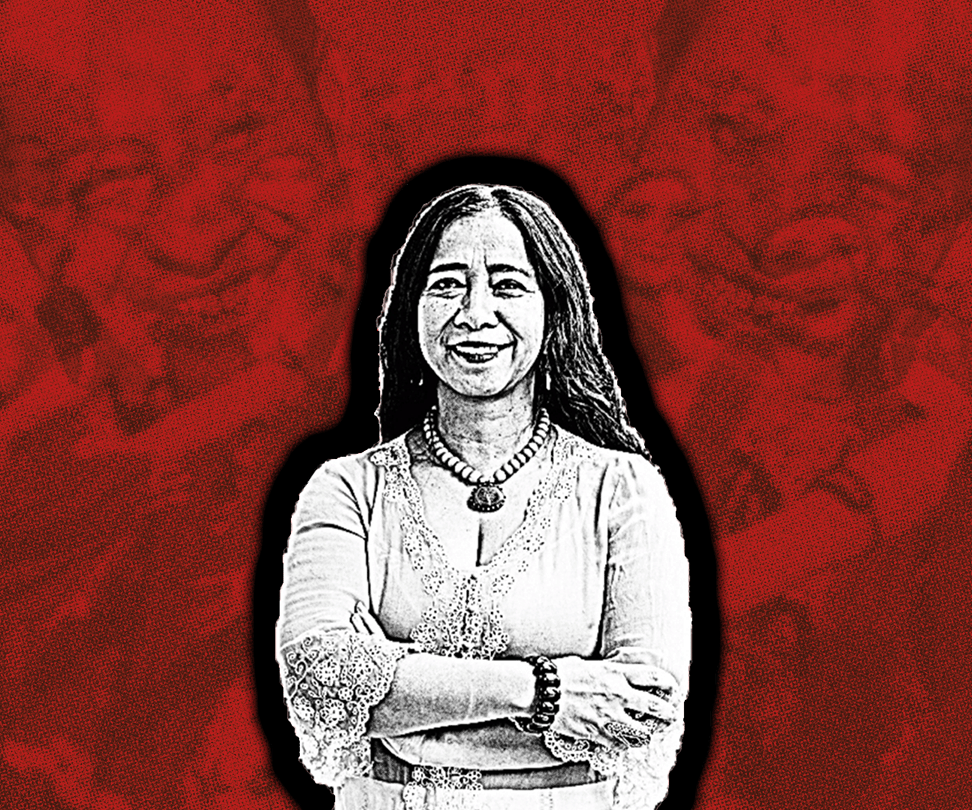
©Ruly/Bal
Pada 2013 lalu, sebuah buku berjudul The Dance That Makes You Vanish: Cultural Reconstruction in Post-Genocide Indonesia selesai ditulis oleh Rachmi Dyah Larasati, profesor di Department of Gender, Women, and Sexuality Studies, University of Minnesota, Amerika Serikat. Buku tersebut mengulas indoktrinasi Orde Baru tentang Peristiwa 1965 yang berdampak kepada usaha rekonstruksi pemerintah dalam aspek kebudayaan. Selain itu, wanita yang kerap disapa Rachmi ini membahas kebijakan-kebijakan kebudayaan pada masa pemerintahan Orde Baru dengan berbekal ingatan masa kecil serta keahliannya dalam bidang kebudayaan dan gender.
Berangkat dari fenomena yang dibahas dalam buku tersebut, BALAIRUNG berkesempatan untuk berbincang dengan Rachmi pada Sabtu (26-11-2022). Ia mengungkapkan bahwa proses penulisan bukunya ini tidaklah mudah. Rachmi banyak mendapati halangan, seperti diintimidasi dan dituduh tergabung dalam partai politik tertentu. Bahkan, ia juga menyampaikan pengalaman penyensoran yang pernah ditujukan kepada karyanya ini.
Namun bagi Rachmi, produksi pengetahuan memang tidak selalu mulus dalam prosesnya sehingga ia tetap berani menulis bukunya. Oleh karena itu, wacana yang dibawakan dalam bukunya ini memang harus disampaikan. Berikut wawancara lengkapnya.
Menurut Anda, apa makna dari istilah “rekonstruksi kebudayaan”?
Rekonstruksi kebudayaan ini bukan soal “kebudayaan itu tidak ada lalu diadakan kembali”. Jadi, bukan tentang itu. Rekonstruksi kebudayaan di sini artinya bagaimana sebuah mekanisme kuasa mengatur, menegosiasi, mengolah, memikirkan, dan mewujudkan di dalam tata laku pengaturan serta pengadaan kebudayaan.
Jadi bukan sebuah “Oh ada budaya, jadi diadakan,” tetapi justru budaya itu sudah berlangsung dan ada. Kemudian, budaya itu dihadapkan pada mekanisme kuasa yang ada. Dalam bahasa umumnya disebut kebijakan kebudayaan.
Lalu, bagaimana rekonstruksi kebudayaan pada masa Orde Baru?
Rekonstruksi yang dimaksud pada masa Orde Baru ini bukan tentang membuat suatu kebudayaan yang baru, tetapi mengatur kebudayaan yang ada dalam peraturan kebijakan. Contohnya seperti yang saya tuliskan dalam buku terkait Tari Jejer Gandrung. Tarian tersebut berkaitan erat dengan kehidupan pertanian. Partai Komunis Indonesia (PKI) waktu itu lekat dengan rakyat sehingga tentu berkaitan dengan kehidupan pertanian.
Pemerintah Orde Baru kala itu mengeluarkan aturan secara implisit bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pertanian maka berkaitan juga dengan golongan Kiri sehingga dilarang keberadaannya di negara ini.
Apakah istilah “keragaman kebudayaan” yang diciptakan pemerintah Orde Baru merupakan indikator keberhasilannya dalam usaha melakukan rekonstruksi kebudayaan?
Rekonstruksi kebudayaan pada masa Orde Baru didasari atas beberapa teknik kebudayaan, seperti standardisasi dan universalisasi. Kemudian, hal tersebut diatur pada sebuah kebijakan yang dibuat langsung oleh pemerintah pusat. Kebijakan inilah yang menjadi rekonstruksi kebudayaan, dan pemerintah merealisasikannya dalam institusi-institusi, termasuk sekolah, kampus, dan departemen kebudayaan lainnya. Keragaman budaya itu berarti keragaman kehidupan, keragaman manusia, dan sebagainya. Jadi, antara kebijakan yang tunggal dan kehidupan yang jamak itulah yang menjadi masalah.
Ketika terjadi perubahan kepemimpinan dalam skala kenegaraan, tentu kebudayaan tersebut tidak dapat langsung berubah. Sebab, kebudayaan memiliki sifat epistemologis yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, hal-hal yang menjadi pola, perilaku, dan tata cara dalam melakukan sesuatu yang bersifat kebudayaan tentu berkaitan erat dengan aspek waktu. Oleh karena itu, kebudayaan tidak dapat berubah dengan cepat. Bahkan, walaupun pemerintahan berubah, belum tentu kebijakan kebudayaannya berubah.
Bagaimana Pemerintah Orde Baru berusaha mengintervensi hubungan tubuh atau ruang pelaku seni dengan kesenian itu sendiri melalui rekonstruksi kebudayaan?
Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan standardisasi-standardisasi terhadap kebudayaan, termasuk seni tari. Tarian yang dianggap “kerakyatan” dan “kurang elegan” distandardisasi serta diatur dalam sebuah pembinaan. Pembinaan ini berada dalam mekanisme kebijakan kebudayaan yang bertujuan mengatur gerak penari. Selain itu, kostum-kostum dalam tarian juga “diperhalus” dengan mengacu kepada tarian keraton (misalnya, Jawa dan Bali) yang dianggap sebagai panutan adiluhung dan lebih elegan.
Pembinaan kebudayaan tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan gerak dan bentuk tarian oleh penari agar sesuai dengan yang diinginkan pembuat kebijakan, yakni pemerintah Orde Baru. Pada masa itu, penari yang dianggap melakukan kesenian secara kurang halus dan tidak memenuhi tata cara budaya keraton diwajibkan mengikuti pembinaan-pembinaan untuk memenuhi standar keraton sehingga terlihat lebih adiluhung.
Apakah pembinaan kebudayaan tersebut menempatkan peran penari perempuan dalam bentuk kepatriarkian negara?
Penari perempuan dapat memberi citra kondisi kenegaraannya yang ditunjukkan dengan kelanjutan tradisi. Hal tersebut merupakan beban dan tugas yang diberatkan kepada mereka. Sebagai contoh, kita dapat melihat fenomena penari Tayub. Ketika akan menari, para penari Tayub akan diatur dan ditata sedemikian rupa supaya sisi keperempuanannya terlihat lebih halus. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat itu perempuan menjadi bentuk kontestasi politik negara dengan dasar kebijakan kebudayaan. Namun di samping itu, juga terdapat perempuan yang menari atas dasar keinginannya sendiri sehingga tetap ada ruang berkarya bagi perempuan pada masa itu.
Sikap patriarkis negara tentu sangat berpengaruh. Pada masa itu, penari Tayub atau penari Gandrung dihubungkan ke dalam sebuah mekanisme. Mekanisme tersebut berupa pemberian izin dari negara kepada para penari di saat banyak dari mereka yang tidak diberikan izin untuk menari. Pada masa Orde Baru, penari yang tidak diizinkan menari adalah mereka yang dianggap berada dalam unwanted place (mereka yang dianggap tergabung dalam golongan kiri).
Namun perlu diingat, hal ini dapat menimbulkan sebuah paradoks melalui perdebatan, seperti ‘Ah, kata siapa tidak bisa menari,’ dan ‘Kata siapa tidak bisa berkarya, saya berkarya’. Pasti akan ada hal seperti itu oleh karena sejarah itu tidak monolitik. Mereka yang tidak berada dalam unwanted place merasa bebas dalam berkarya. Hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan kebudayaan tunggal yang mengatur kehidupan jamak dan beragam.
Apakah terdapat kepatriarkian negara sebelum dimulainya pemerintahan Orde Baru dalam konteks penari perempuan?
Kalau membicarakan rezim Sukarno dan rezim Soeharto, tentu ada persamaan dan perbedaannya. Namun, perbedaan tersebut terlihat sangat mencolok dan sangat frontal. Hal itu dikarenakan berdirinya pemerintahan Soeharto didasari pembunuhan massal, sedangkan dasar pemerintahan Sukarno didasari adanya perjuangan. Jadi, kalaupun terdapat kepatriarkian di dalamnya, ada kesejarahan dalam konteks kelahiran yang berbeda secara rasional.
Dalam penelitian arkais saya pada saat pemerintahan Sukarno, ada semacam ruang yang lebih fleksibel antara kerakyatan, keindonesiaan, dan kenusantaraan yang muncul secara berbeda. Pada masa itu, kebudayaan yang terjadi, dalam konteks ini berupa tarian, terlaksana secara lebih rileks. Rileks dalam arti estetika, bukan secara makna. Rileks secara estetika berarti bentuk-bentuk yang ada dalam tarian Jawa, tarian Bali, ataupun tarian Sumatra, di dalamnya ada semacam kerileksan secara estetik-teknik. Ada semacam dedikasi yang lebih kerakyatan.
Sukarno lebih mengarah pada estetika yang sifatnya populer kerakyatan sehingga tidak ada semacam “pembinaan” (sebagaimana di era Soeharto). Walaupun banyak yang berargumen bahwa konteks pendasaran “kerakyatan” itu dipengaruhi oleh kecenderungan Sukarno terhadap keterkaitan dengan partai politik yang berideologi komunis di Indonesia. Sikap patriarki negara tentu tetap ada, baik pada masa Sukarno maupun Soeharto, sedangkan rasional epistemologi kehidupan berbudayanya-lah yang berbeda.
Pemerintah merealisasikan rekonstruksi kebudayaan dengan cara menghilangkan tubuh-tubuh yang dianggap “kotor” dan digantikan dengan tubuh baru yang “bersih”. Berdasarkan hal tersebut, apakah eksistensi keaslian suatu kesenian yang ditarikan ulang sudah hilang sehingga pemerintah sama saja menciptakan kebudayaan yang baru?
Autentisitas atau keaslian di dalam kesenian itu sebetulnya tidak begitu penting. Karena yang penting adalah keaslian dedikasi dan tujuannya. Kesenian adalah kreativitas dan sebuah dunia imajinasi. Sehingga, keaslian dedikasi itu lebih pada dedikasi kemanusiaan dan tujuannya.
Mengapa Anda memilih Tari Jejer Gandrung sebagai tarian yang banyak dikaitkan dengan rekonstruksi kebudayaan oleh pemerintah dalam buku Anda?
Tarian Jejer Gandrung yang dekat dengan rakyat dan berhubungan dengan dunia pertanian dianggap dekat juga dengan PKI. Namun, tiba-tiba terjadi perubahan politik yang luar biasa. PKI yang dulunya legal dan dilindungi oleh konstitusi, tiba-tiba jadi membahayakan negara. Peristiwa ini adalah perubahan yang luar biasa dan Tari Jejer Gandrung yang sebenarnya memiliki konteks sebagai pengingat dan memiliki nilai yang luar biasa pun mengalami perubahan.
Dari anggapan perempuan yang menari adalah sumber pengetahuan, kemudian dianggap menjadi perempuan penggoda. Agama kemudian dipakai dari sistem kapitalis ini untuk mengatakan dan mengatur tarian-tarian tersebut. Latar belakangnya sebetulnya yang lebih berbahaya. Bahayanya adalah yang berkolaborasi dengan eksternal politik dengan dunia pangan kemudian dianggap secara tidak langsung berkolaborasi waktu itu dengan keagamaan karena memakai bahasa tubuh yang dianggap di luar kesopanan dan kenormaan yang bisa diterima.
Apakah rekonstruksi kebudayaan juga berdampak bagi masyarakat umum yang tidak berkaitan dengan organisasi kebudayaan, komunisme, atau bahkan kesenian itu sendiri?
Rekonstruksi kebudayaan sangat berdampak secara nasional, baik yang terlibat partai politik, organisasi kebudayaan, maupun di luar itu semua. Hal tersebut dikarenakan kita semua hidup bersosial. Apalagi waktu itu, PKI merupakan partai besar dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan organisasi kesenian yang lain tidak semuanya termaktub di dalam keanggotaan. Mereka yang dianggap tidak diinginkan maka akan dipenjara, dibunuh, atau keseniannya dihilangkan. Sedangkan di luar itu, tentu mengalami dampaknya tapi dalam konteks dan kondisi yang berbeda.
Bahkan di dalam buku saya dijelaskan bahwa ada pergantian tubuh-tubuh pelaku kesenian. Maka dari itu, sampai sekarang sulit untuk memahami ini. Karena jika sudah menjadi bagian yang melupakan, tentu sangat mudah untuk terus melupakan. Bukan berarti orang-orang baru ini tidak baik, tetapi ada semacam “ruang pelupaan” atau mekanisme yang dilupakan di dalam memahami sisi kemanusiaan dari tarian-tarian tersebut. Bukan berarti tarian-tarian yang sekarang tidak mampu melahirkan konteks pengetahuan, namun terdapat jarak yang terjadi secara kesejarahan.
Penulis: Yasmin Nabiha Sahda, Farida Ratnawati, dan Nandini Mu’afa
Penyunting: Lindra Prastica
Illustrator: Ruli Andriansah