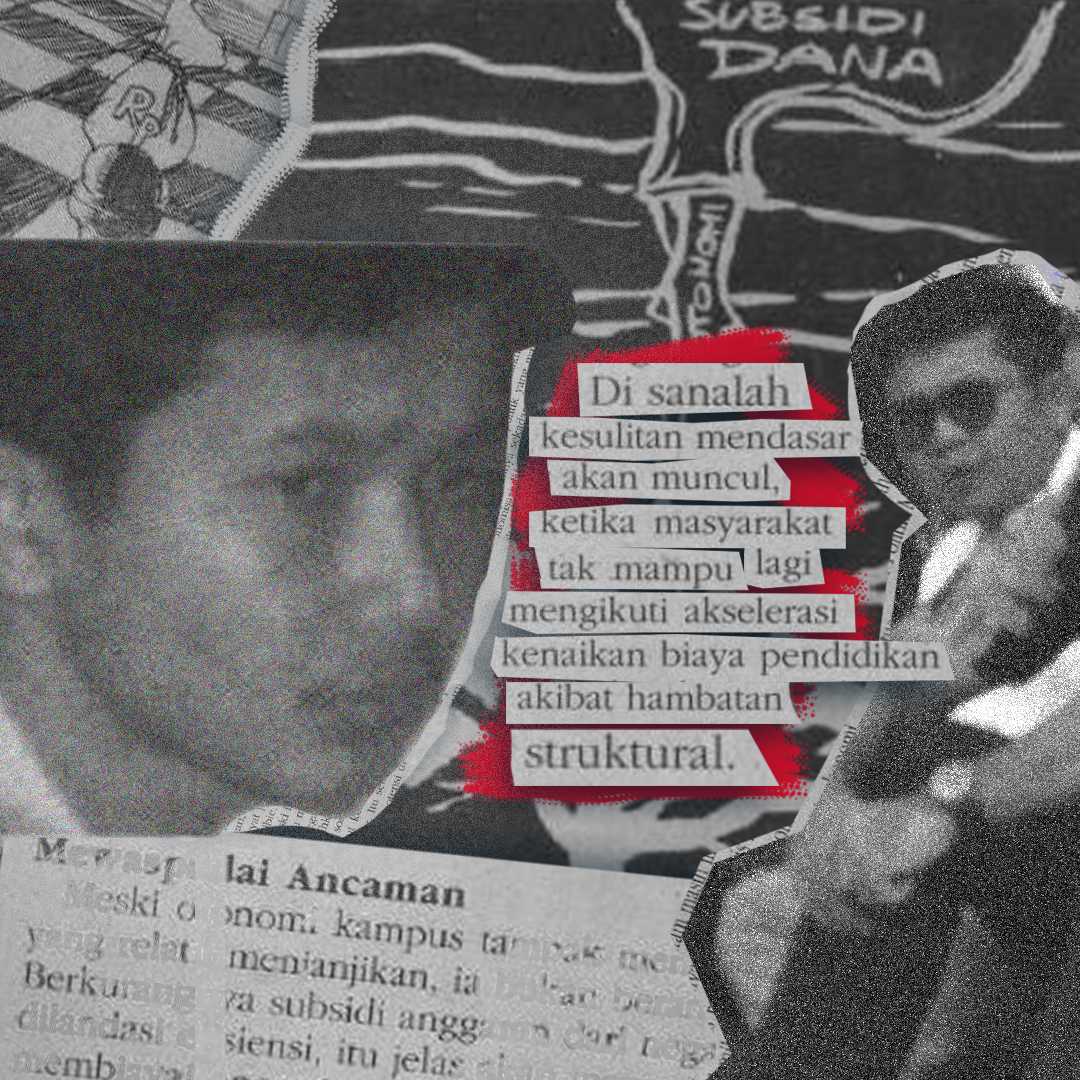
©Rezi/Bal
Wacana otonomi kampus kembali mencuat di tengah krisis ekonomi negara pasca-Reformasi. Ketidakmampuan negara dalam memberi subsidi kepada perguruan tinggi menjadi alasan. Kala itu, seorang Staf Pengajar Sosiologi UGM mencoba mengulas kebijakan otonomi kampus. Menurutnya, kebijakan otonomi kampus rawan terjerumus dalam pendelegasian peran hegemoni: dari hegemoni negara kepada hegemoni kapitalisme atas perguruan tinggi.
Kini, staf pengajar itu adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada untuk masa bakti 2022–2027. Ia adalah Arie Sudjito. Dalam berbagai kebijakan UGM untuk menarik dana dari masyarakat, BALAIRUNG menerbitkan ulang Opini Arie Sudjito yang terbit dalam Majalah BALAIRUNG Edisi Khusus/Th. XV/1999.
Keprihatinan yang dalam masih melanda Indonesia. Diawali munculnya “sekadar” krisis moneter, kemudian berubah menjadi bencana ekonomi. Hanya butuh waktu yang demikian kilat, secara eskalatif, krisis ekonomi berdampak kepada lahirnya prahara politik. Negeri yang selama 32 tahun “tampak harmonis” ini akhirnya kalut. Tahap pertama krisis ekonomi-politik itu mencapai klimaksnya ketika Sang Tiran, Soeharto, dipaksa turun takhta oleh gerakan mahasiswa-rakyat pada 21 Mei 1998. Lalu, disusul sang penguasa darurat, Habibie, yang cuma berkuasa satu setengah tahun.
Meski intensitas krisis reda, namun problem sosial-bangsa saat itu makin meluas. Pergantian pimpinan baru, duet Gus Dur-Megawati, yang berarti untuk sementara berhasil memulihkan kepercayaan politik, bukan berarti konflik-konflik sosial usai. Pergolakan meletup di berbagai daerah, menuntut kemerdekaan—beberapa orang menyebutnya separatisme. Itu semua, tentunya, menjadi catatan awal bagi terbentuknya potensi disintegrasi bangsa.
Tak bisa dimungkiri, krisis ekonomi-politik ini telah “berhasil” mengoyak berbagai aspek struktural masyarakat. Tak terkecuali dengan dunia pendidikan kita. Di tengah suasana itu, terlontar niatan pemerintah untuk menerapkan otonomi kampus. Meski bukan ide baru, otonomi kampus sempat menyedot perhatian banyak kalangan, khususnya insan kampus yang relatif memiliki kepentingan di dalamnya.
Dulu, ide otonomi kampus ini mulai dipopulerkan sekitar awal 1990-an. Gelombang protes dimotori mahasiswa dan elemen sivitas akademika yang menuntut diterapkannya otonomi kampus, tak lain, sebagai respons atas gejala dependensi kampus akibat hegemoni negara. Tuntutannya sederhana saja: agar negara tak berlebihan melakukan intervensi. Kampus ingin ditempatkan secara otonom; hak-hak warga kampus, baik akademis maupun sosial-politik, mesti diterapkan. Misalnya, kebebasan dalam penentuan kurikulum, berkreasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, berorganisasi, serta otoritas penentuan pemimpin kampus.
Hak mahasiswa berorganisasi menjadi topik penting. Tahun 1991, misalnya, mahasiswa UGM, ITB, UI, serta universitas-universitas swasta berdemonstrasi menolak keberadaan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi sebab dianggap sebagai agen kendali negara atas mahasiswa. Umumnya, mereka menolak politik korporatisasi. Meski diakhiri dengan kompromi minimalis, kesadaran untuk melawan terus berkembang kala itu. Apalagi, hal itu didasari kuatnya posisi negara, dengan politik represi yang demikian dominan.
Kegiatan ilmiah seperti diskusi harus memperoleh izin dari aparat. Para aktivis/demonstran mahasiswa ditangkapi. Tokoh-tokoh kritis pun dicekali. Bahkan, negara tak memberi kesempatan sedikit pun kepada masyarakat kampus untuk menentukan pemimpinnya. Tahun 1994 mahasiswa yang tergabung dalam Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima) UGM menolak keputusan pemerintah dalam penentuan rektor UGM. Para mahasiswa ini menolak rektor “drop-dropan”. Alasannya, cara itu dianggap tidak demokratis karena tak sesuai dengan aspirasi mahasiswa sebagai mayoritas warga kampus. Hal yang sama berlangsung pula di universitas-universitas lainnya. Fakta-fakta itu, sedikitnya, dapat dijadikan argumen untuk memahami maraknya protes-protes mahasiswa bersama dosen dalam tuntutan ditegakkannya otonomi kampus.
Kebijakan depolitisasi, deideiologisasi, dan floating mass ‘massa mengambang’ melalui desain korporatisme membuat kampus mandul dan statis. Pembonsaian ini memang dikonstruksi oleh negara agar kampus termobilisasi dan terintegrasi pada “pembangunan”. Pembangunan di sini dimaknai dalam parameter economy growth ‘pertumbuhan ekonomi’ dan politik yang mapan. Tak pelak, kampus umumnya sekadar menjadi arena proses ekonomisasi dan birokratisasi. Prestasi kampus diukur melalui tingkat loyalitas dalam melaksanakan pembangunan. Kenyataan itu jelas menjadi hambatan mendasar upaya pemberdayaan (empowerment) kampus sebagai agen demokratisasi. Kampus tidak lagi independen dalam mengemban misi pendidikan bangsa.
Sayangnya, keresahan-keresahan itu tak terlalu mendapatkan porsi besar perhatian publik, apalagi tanggapan positif negara. Sebaliknya, diskursus otonomi kampus justru dianggap “subversif-akademis” akibat tafsir “kemerdekaan kampus” sebagai bentuk ancaman sistematik atas kekuasaan. Akibatnya, wacana otonomi kampus menguap tak berbekas. Karena itu, jika pada masa transisi demokrasi saat ini muncul ide otonomi kampus, ia bukan merupakan isu baru, kecuali ia memiliki konteks yang berbeda serta menemukan momentumnya untuk diungkap kembali.
Konteks Otonomi
Membaca setting sosiopolitiknya, kebijakan yang bakal diintrodusir pada 2000, dan dieksperimentasikan pada empat perguruan tinggi (PT) terbesar di Indonesia (UGM, ITB, UI, dan IPB), itu tampaknya diletakkan pada dua konteks alasan signifikan.
Pertama, sebagai resultante aliran reformasi, political will ini dapat dimengerti sebagai bentuk reaksi atas gagalnya negara memberi jaminan sosial berupa subsidi pada perguruan tinggi, terutama akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut hingga kini. Kapasitas struktural negara yang merosot memaksa PT mencari sendiri alternatif sumber dana guna menopang operasionalisasi pendidikan.
Kedua, seiring dengan akselerasi perkembangan global, institusi PT memang dihadapkan kepada tantangan besar: kompetisi internasional yang tajam. Hal ini berarti relasi dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tak hanya dipagari pada level lokal atau nasional, tetapi justru, mau tak mau, memasuki zona internasional. Dalam konteks itu, secara kelembagaan, PT dituntut lebih fleksibel: menghilangkan struktur dan kultur yang kaku serta birokratis.
Menimbang Peluang
Kondisi negara yang miskin, seperti tersebut dalam konteks pertama, dapat dipahami sebagai isyarat hilangnya alasan kendali oleh negara atas dunia PT. Itu berarti, PT relatif berpeluang keluar dari lingkaran ketergantungan atas hegemoni (politik) negara. Perubahan-perubahan dalam hal pendanaan, contohnya, menjadi faktor penting premis di atas. Beban dana 40% lokal (beban PT masing-masing) dan 60% nasional (beban negara) menjadi 65% lokal dan 35% nasional pada desain otonomi kampus. Selebihnya pula, PT leluasa mengelola administrasi kepegawaian. Misalnya, status dosen serta karyawan dikonversikan, dari PNS menjadi pegawai institusi kampus, dan bertanggung jawab hanya kepada PT masing-masing.
Model seperti itu tentu tak menuntut pertanggungjawaban politik kepada negara, kecuali pertanggungjawaban akademik dan manajerial kepada publik atau masyarakat. Dengan demikian, sivitas akademika jauh berpeluang mengembangkan kreativitas dan leluasa berimajinasi dengan pengetahuannya tanpa harus disensor oleh penguasa.
Selebihnya, jika otonomi kampus ini diterapkan melalui basis konseptual, visi, misi, dan program kerja yang jelas serta aplicable; ia akan menjadi peluang besar bagi PT untuk merintis relasi kelembagaan dengan lembaga-lembaga internasional, tanpa melalui jalur birokrasi yang berbelit-belit. Pengembangan ilmu pengetahuan dan ragam informasi yang signifikan bagi proses belajar-mengajar menjadi lebih mudah dilakukan, tanpa dibatasi kepentingan politik negara. Akses bagi mobilitas PT menjadi lebih terbuka. Jalinan kerja sama internasional untuk mengucurkan dana, beasiswa studi mahasiswa dan dosen, serta pengembangan kelembagaan—untuk sedikit contoh—bukanlah sesuatu yang mustahil untuk direngkuh.
Mewaspadai Ancaman
Meski otonomi kampus tampak menawarkan masa depan yang relatif menjanjikan, ia bukan berarti tanpa persoalan. Berkurangnya subsidi anggaran dari negara, yang katanya dilandasi efisiensi, jelas akan menambah beban PT untuk membiayai operasionalisasinya. Maka, bukan mustahil jika muncul alasan rasionalisasi penyerapan dana, khususnya bersumber dari masyarakat, misalnya melalui SPP. Melambungnya SPP mahasiswa yang akhir-akhir ini terjadi, agaknya, merupakan “pemanasan” awal sebelum diterapkannya kebijakan otonomi kampus. Demikian pula, perguruan tinggi “dipaksa” untuk mencari peluang berdagang demi biaya hidup lembaga. Jangan heran jika kampus akhirnya ibarat “perusahaan pendidikan” yang memiliki macam-macam usaha, seperti minyak (pompa bensin), mal, percetakan, toko buku, dan usaha-usaha lainnya yang terjangkau.
Sekolah menjadi mahal dan terjadi privatisasi pendidikan. Hipotesis ini jelas mengasumsikan bahwa kemampuan struktural masyarakat tumbuh secara positif dengan nilai kenaikan dana pendidikan tersebut. Padahal, dalam kenyataan empiris, daya ekonomi masyarakat jelas mengalami kemerosotan, khususnya sebagai akibat langsung benturan krisis ekonomi. Di sanalah kesulitan mendasar akan muncul: ketika masyarakat tak mampu lagi mengikuti biaya pendidikan akibat hambatan struktural.
Otonomi kampus juga memberikan ruang bagi terbangunnya relasi dengan sistem global. Kenyataan ini memang memaksa negara untuk menciutkan peran dan kendalinya terhadap sistem pendidikan di PT.
Situasi selanjutnya beralih kepada interaksi perguruan tinggi dengan globalisme. Artinya, penetrasi ideologi global, kapitalisme misalnya, menjadi hal yang perlu dipertimbangkan efeknya. Ada keyakinan, dilandasi oleh tuntutan pasar kapitalisme, orientasi pendidikan pun “dipaksa” untuk berintegrasi dengan kemauan pasar itu sendiri. Jangan heran jika muncul sejumlah kekhawatiran, yakni bakal ditutupnya jurusan-jurusan yang dianggap “tak laku dijual di pasar” meski ia teramat penting sebagai ilmu pengetahuan.
Karena itu, salah-salah, otonomi kampus hanyalah bentuk pendelegasian peran hegemoni: dari hegemoni negara kepada hegemoni kapitalisme atas PT. Siapkah perguruan tinggi merespons secara kritis kecenderungan ini?
Arie Sudjito
Staf Pengajar Sosiologi UGM
Artikel ini ditulis ulang dengan penyuntingan oleh Ryzal Catur.