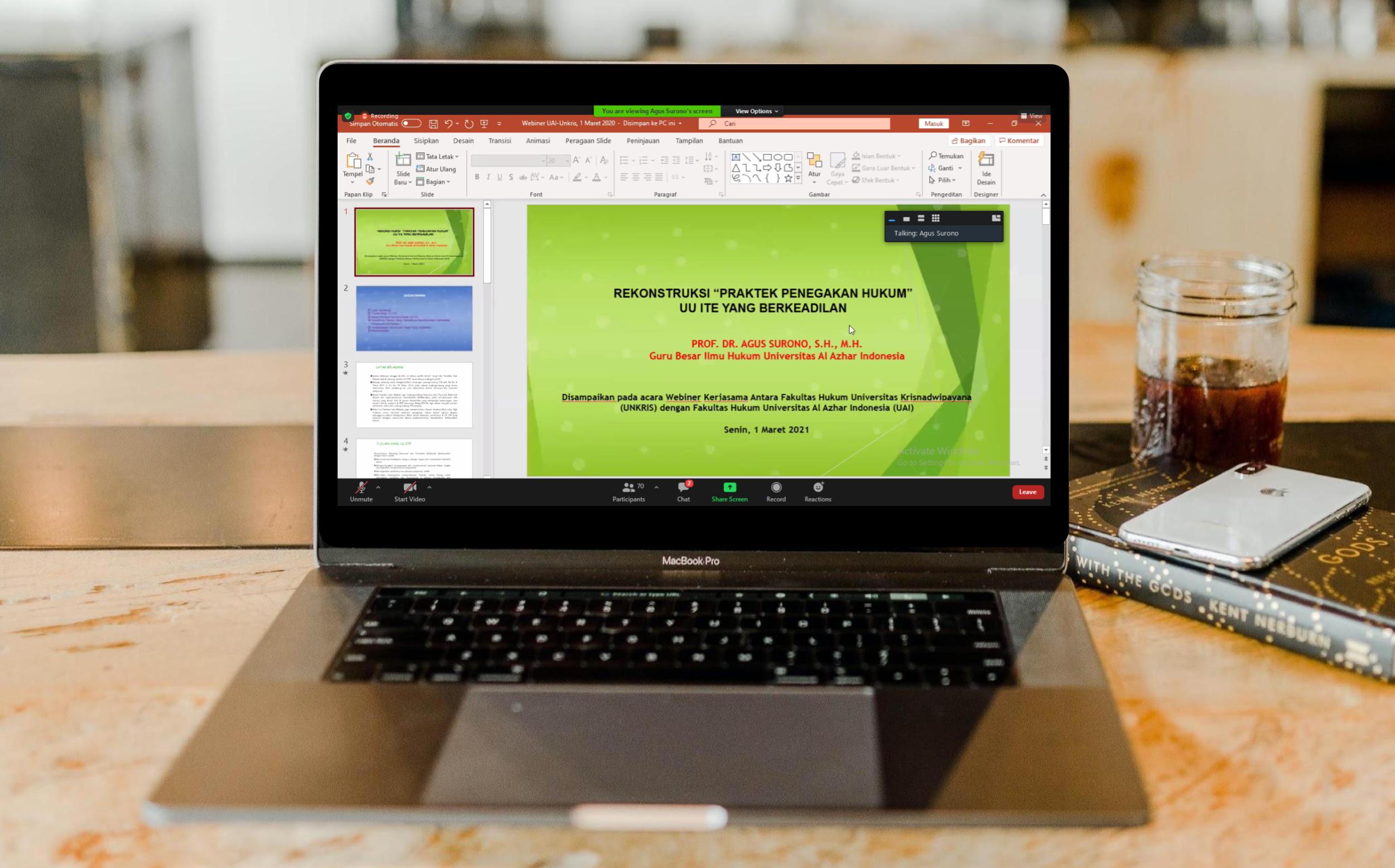
©Isabella/Bal
Banyaknya laporan hukum yang diajukan oleh beberapa pihak menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memicu timbulnya berbagai spekulasi. Kemudahan suatu pihak untuk mengajukan tuntutan yang menyangkut pelanggaran UU ITE menunjukkan adanya kemungkinan kekeliruan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan UU ini. Menanggapi kondisi itu, Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) bekerjasama dengan Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) mengadakan diskusi bertajuk “Urgensi dan Rekonstruksi Revisi UU ITE yang Berkeadilan” pada Senin (01-03).
Diskusi yang diselenggarakan secara daring ini menghadirkan empat narasumber, di antaranya Agus Surono, Guru Besar Ilmu Hukum UAI; Firman Wijaya, Kepala Program Studi Doktoral UNKRIS; Hartanto, Sekretaris Pascasarjana dan Doktoral UNKRIS; dan Buni Yani, pegiat media sosial. Menghadirkan pula Asep Saefuddin selaku Rektor UAI sebagai pembicara utama, diskusi yang dipandu oleh T. Taufik Lubis ini membahas mengenai urgensi dari revisi UU ITE yang sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo di pertengahan Februari lalu.
Dalam pemaparannya, Taufik menyampaikan bahwa tujuan awal dibentuknya UU ITE ini ditujukan sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia saat memasuki era informasi digital. Menurutnya, adanya UU ini dapat menjadi awal yang baik bagi masyarakat. “Diharapkan masyarakat dapat menikmati ruang-ruang digital tanpa merugikan kepentingan pribadi maupun kelompok,” ungkapnya.
Senada dengan hal itu, Agus juga mengungkapkan perihal alasan UU ITE dibentuk melalui perspektif hukum. Ia menjelaskan, adanya UU ITE dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Namun, di tengah penerapanya, UU ini rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Taufik, UU ITE telah dijadikan instrumen atau alat untuk memukul dan menyerang lawan politik. “Keberadaan UU ini menjadi mengkhawatirkan bagi semua pihak karena adanya penyalahgunaan dibaliknya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus menyoroti perihal pasal-pasal yang dianggap multitafsir dalam UU ITE. Dalam penjelasannya, ia mengungkap pasal-pasal yang dipersoalkan oleh publik. Pertama, Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) mengenai penghapusan informasi. Kedua, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) tentang penghinaan serta pencemaran nama baik. “Adanya pasal karet ini mengakibatkan banyak kasus memiliki perbedaan tafsir oleh aparat penegak hukum,” tandasnya.
Mereka yang lantang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah baik itu aktivis maupun akademisi terkadang turut menjadi korban. Mengutip dari yang disampaikan Agus Surono pada UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) terkait penghinaan dan pencemaran nama baik menimbulkan problem hukum. “Adanya gradasi pencemaran tingkat hukum yang sebenarnya ini merupakan duplikasi dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP,” jelasnya. Duplikasi kedua pasal ini membuat cakupan pidana mengenai pencemaran nama baik menjadi sangat luas.
Senada dengan Agus Surono, Buni Yani seorang pegiat sosial media mengatakan bahwa sekarang ini banyak sekali aktivis yang dikriminalisasi akibat multi tafsirnya pasal-pasal dalam undang-undang ini. Menurutnya kritikan-kritikan lewat sosial media yang sebagian besar ditujukan kepada pemerintah sebetulnya merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Rakyat berhak mengutarakan pendapatnya di muka umum yang dalam hal ini kita sebut sebagai kebebasan berpendapat. Tetapi, kritik yang cenderung subjektif dan bersifat menyerang individu atau personal tentu tidak dibenarkan.
Menurut Hartanto, revisi UU ITE akan relevan dan bermanfaat kepada masyarakat jika memberikan kepastian hukum. “Revisi UU ITE dapat melindungi masyarakat dari kejahatan yang berbasis teknologi,” jelas Hartanto. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dalam proses revisi UU ITE diperlukan ketegasan agar tidak menghasilkan produk yang multitafsir.
Selain revisi, kehadiran pedoman untuk memberikan batasan terhadap penafsiran UU ITE diperlukan. “Buku putih dan beberapa instrumen harus diterbitkan,” tegas Firman. Bagi Firman, pengadaan buku putih dapat menjadi alternatif untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi dari UU ITE dan juga melahirkan instrumen hukum tambahan. Seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai UU ITE.
Penulis: Akhmad Fadhilah Santoso , Annisa Shafa Regina, dan Jacinda Nuurun Addunyaa
Penyunting: Isabella