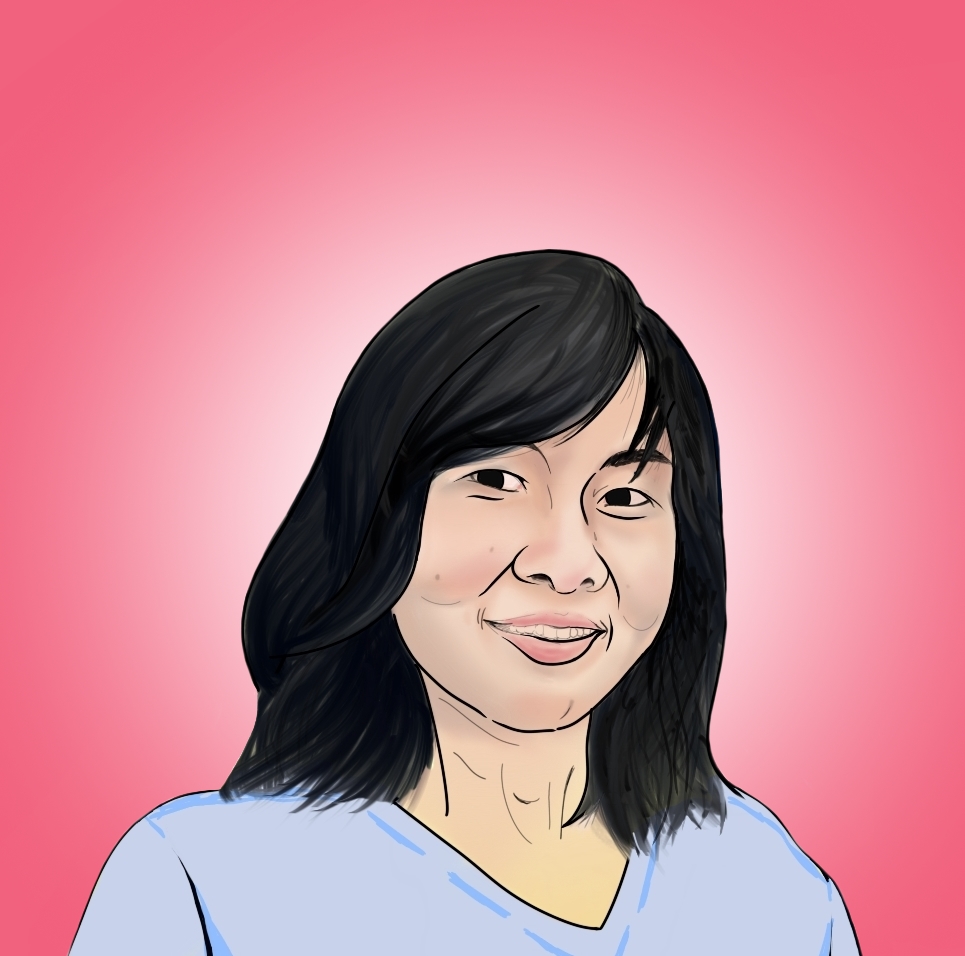
©Sidik/Bal
Sejarah genosida 1965 diperingati setiap tahun, namun kebenaran dari muatan sejarahnya masih menimbulkan tanda tanya. Peristiwa yang menandai sejarah kelam Indonesia ini masih disangsikan oleh masyarakat Indonesia. Pasca Amerika Serikat merilis dokumen bukti genosida ‘65, fakta-fakta sejarah baru terus terkuak dan disuarakan dengan nyaring kepada masyarakat.
Soe Tjen Marching adalah salah satu penulis Indonesia yang berani mengulik isu-isu genosida ‘65, terlebih ia juga merupakan bagian dari keluarga penyintas ‘65. Semangat untuk menyuarakan kebenaran menjadi dasar perjuangannya. Motivasi tersebut mampu menghasilkan banyak karya yang membuka mata pembaca akan sisi lain narasi buatan Orba yang telah berkembang di masyarakat.
Perjuangannya tertuang dalam dua karya, yaitu berupa buku akademik The End of Silence dan karya fiksi Dari Dalam Kubur. Kedua karyanya menilik cerita kekejaman yang dialami korban dan berusaha mengungkap fakta sejarah genosida ‘65. Karya ini lahir sebagai media untuk menggemakan suara para korban yang ingin didengarkan. BALAIRUNG berkesempatan untuk menggali pandangan Soe mengenai dampak dari stigmatisasi yang mengakar terhadap korban dan keluarga mereka yang ditumpahkan melalui karya miliknya.
Bagaimana bentuk kekejaman yang dialami oleh korban?
Penyiksaan bersifat massal, dilakukan oleh beberapa orang terhadap korban. Di dalam penjara penyiksaan bisa berupa disulut rokok, bahkan puting payudara mereka, dan diperkosa beramai-ramai. Ada objektivitas terhadap perempuan di dalam penjara. Hal ini dilandasi oleh anggapan mereka yang memperlakukan perempuan layaknya ‘barang’. Belum lagi, kesan yang diberikan oleh negara kepada para pelaksana lapangan untuk melakukan keleluasaan bersikap sewenang-wenang terhadap perempuan. Perlakuan ini tidak hanya terjadi di dalam penjara. Di luar penjara, pernah terjadi juga hal serupa. Seorang lurah perempuan yang dianggap sebagai anggota PKI, diseret dengan keadaan telanjang. Lalu dibakar kemaluannya dan dipotong hidup-hidup.
Dampak seperti apa yang dirasakan oleh korban pasca genosida ‘65?
Dampak yang dirasakan oleh para korban berupa trauma yang luar biasa, serta amarah yang tinggi. Sebab, penyiksaan masih terus hadir dalam ingatan para korban. Korban seringkali memisahkan diri dari masyarakat, tetapi bagaimanapun keluarga tidak dapat dipisahkan. Tentu ini berdampak pada keluarga para korban. Amarah dan frustasi para korban tersalurkan kepada keluarga. Alhasil, hal ini seringkali memicu hubungan keluarga menjadi kacau.
Bagaimana hubungan antar keluarga selanjutnya? Walaupun ada keluarga yang menerima dengan terpaksa, lebih banyak yang menolak secara mentah-mentah keberadaan korban. Di lain sisi, masih banyak keluarga korban yang belum memahami peristiwa pembantaian ‘65. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri masih terdapat keluarga yang memihak kepada rezim Orba. Ketidaktahuan ini yang memicu kebencian keluarga terhadap korban.
Dampak kepada perempuan jauh lebih besar. Bukan hanya mengalami trauma setelah dipenjara, namun juga dipisahkan dari anak-anak mereka. Akibat stigma yang lebih besar terhadap perempuan, dampak emosional itu begitu mendalam karena semua yang dialaminya disimpan rapat-rapat sendirian. Frustasi dan kemarahan yang tidak tersalurkan masih membekas sampai tua.
Apa dampak yang dirasakan oleh keturunan korban?
Keturunan korban masih terus dirundung ketakutan. Usaha untuk membuka fakta sejarah ini masih terus mendapatkan ancaman dan tuduhan. Mungkin saya masih lebih beruntung dari keturunan korban lainnya karena saya memiliki kesempatan untuk menyuarakan isu ini. Namun, keturunan lainnya masih mendapatkan tindakan tidak menyenangkan hingga saat ini. Mereka dibatasi suaranya oleh stigma yang melabeli mereka layaknya musuh negara.
Apa yang mendasari pembungkaman terhadap fakta sejarah?
Stigma-stigma yang melekat pada korban pada akhirnya digunakan untuk membungkam mereka. Tindakan represif termasuk ancaman yang menyasar pada korban masih dilanggengkan. Bahkan, negara abai terhadap suara korban maupun kami yang berbicara berdasarkan dokumen dan bukti. Tindakan mengancam ini seolah-olah terus dibiarkan oleh negara sehingga telah tersebar luas. Hingga saat ini narasi yang menstigmatisasi korban masih digaungkan di masyarakat. Hal itu yang kemudian membungkam fakta sejarah.
Mengapa stigmatisasi ini masih mengakar hingga sekarang?
Hal ini karena kroni-kroni Orba yang masih berkuasa. Reformasi hanya berhasil menurunkan Soeharto, tetapi ideologi Orba masih langgeng. Kalau saya coba bandingkan dengan genosida di Jerman, sejarah langsung diganti dan dikritik, monumen yang keliru dihancurkan, dibangun monumen baru yang memperingati kematian genosida. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab dikejar dan ditangkap, sedangkan korban diberi kompensasi. Di negara kita, bahkan permintaan maaf dan pengakuan terhadap sejarah yang salah belum mampu dilakukan. Monumen dan patung masih dibiarkan, narasi sejarah masih dikembangkan, juga belum ada perlindungan terhadap korban. Ini sangat penting untuk diselesaikan. Sejarah sejatinya harus diceritakan dengan jujur dan adil. Bukan hanya dari satu pihak untuk kepentingan tertentu saja.
Bagaimana dengan peran negara dalam merangkul dan memulihkan nama baik korban?
Negara sudah banyak diberi kesempatan untuk membarengi korban. Pengadilan rakyat tahun 2015 sudah menetapkan bahwa pemerintah bersalah terhadap genosida dan pemerkosaan besar-besaran. Kami tidak menuntut banyak, hanya mengajukan saran ke pemerintah untuk minta maaf dan mengubah sejarah yang berkembang. Para penyintas cukup puas jika pemerintah dapat meluruskan sejarah sebagaimana mestinya karena yang mereka perjuangkan adalah kebenaran. Mereka bahkan tidak meminta kompensasi apapun meski sudah dimiskinkan akibat dari peristiwa itu. Namun, hal tersebut belum juga diwujudkan. Bukannya menghapus stigma, korban terus direpresi. Kami akhirnya saling tolong satu sama lain tanpa uluran tangan negara.
Tanpa kepastian dan jaminan dari negara berkaitan dengan penyiksaan, hingga saat ini hanya akan menambah trauma. Tidak hanya kepada korban namun keluarga korban dan generasi penerusnya. Permasalahan sebesar ini selalu ditutup-tutupi. Jika luka ini tak kunjung diakui, maka akan memberikan kemungkinan timbulnya luka-luka baru yang dibuat tanpa harus takut diadili. Kejadian nyata sudah terjadi di Timor Leste dan Aceh. Oknum tentara melakukan pemerkosaan dengan pemikiran bahwa hal tersebut bisa terus disembunyikan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap peristiwa pembantaian ‘65 menjadi sangat penting.
Lalu, upaya apa yang harus dilakukan untuk membuka mata masyarakat akan fakta sejarah ini?
Masih banyak hal yang perlu kita tuntaskan. Apalagi kurikulum pendidikan Indonesia khususnya mata pelajaran sejarah masih menggunakan versi Orba. Hal ini sangatlah fatal, karena pasti sudah berjuta-juta orang meyakini atas sejarah versi tersebut. Banyak monumen dan museum yang lestari sampai saat ini merupakan peninggalan Orba.
Pertama, pemerintah harus meyakini sejarah yang asli dan sebenar-benarnya. Kedua, merombak pendidikan Indonesia menjadi kurikulum sejarah yang tepat. Ketiga, menyelesaikan hal yang lain seperti mengubah teks sejarah, museum, dan monumen. Ini perlu segera diselesaikan mengingat doktrin sejarah oleh Orba di kalangan masyarakat sudah mengakar.
Selain itu, masyarakat harus mau membuka diri terhadap sumber-sumber sejarah lain. Berkutat hanya pada narasi yang disuapi negara tanpa melihat dari sudut pandang lain akan menjebak kita dalam propaganda. Upaya ini bisa menjadi perjuangan dalam merobohkan stigmatisasi yang menghantui korban genosida ‘65.
Penulis: Antonella, Jacinda Nuurun A, Salsabila Safa (Magang)
Penyunting: Salsabella ATP
Ilustrator: Sidik Legowo (Magang)
erata: “disulut rokok, puting, dan diperkosa oleh beberapa sipir” diubah menjadi “disulut rokok, bahkan puting payudara mereka, dan diperkosa beramai-ramai”.
1 komentar
Wawancara berkelas, upaya menyingkap tabir sejarah kelam terhadap tragedi Genosida’65…👍