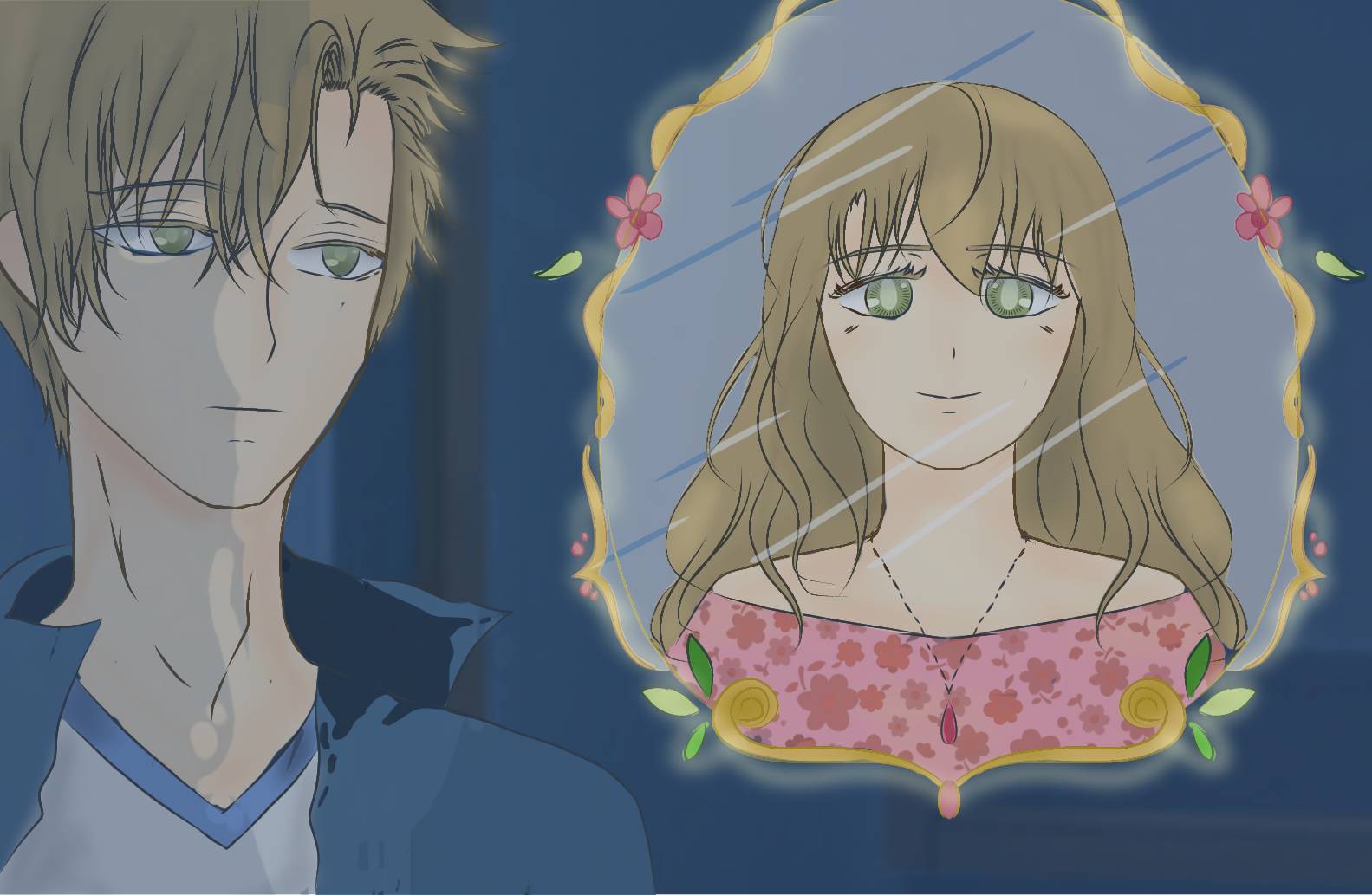
©Laras/Bal
Sejumlah orang di dunia terjebak dalam identitas yang tidak mereka inginkan. Identitas ini disematkan kepada mereka saat lahir sebagai bentuk konformasi terhadap dikotomi gender dalam masyarakat.
Berbicara mengenai citra diri tentu tidak dapat berlepas diri dari identitas gender, terlebih apabila berbicara mengenai bagaimana seseorang menerima dan melihat dirinya sendiri. Identitas gender umumnya dikaitkan dengan karakteristik biologis seperti jenis kelamin. Karakteristik biologis ini kemudian menghasilkan dikotomi gender, di mana gender bagi pemilik penis adalah laki-laki dan gender bagi pemilik vagina adalah perempuan. Nyatanya, tidak semua orang merasa memiliki identitas gender yang sesuai dengan karakteristik biologis yang ia miliki sejak lahir. Dulu, rasa inkongruen ini dapat didiagnosis dengan sebutan gangguan identitas gender (gender identity disorder). Namun, kini nama tersebut direvisi menjadi disforia gender dalam buku panduan terbaru Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) untuk menekankan bahwa disforia gender tidak memahami nonkonformitas gender sebagai sebuah gangguan mental (American Psychiatric Association, 2013). Disforia gender (gender dysphoria) adalah diagnosis bagi seseorang yang merasakan tekanan mental karena pengalaman subjektif dirinya sebagai identitas gender yang berbeda dengan identitas yang dilabelkan kepadanya saat lahir. Diagnosis ini lebih fokus pada ketidaknyamanan, kegelisahan, dan beban pikiran yang dialami oleh orang dengan disforia gender.
Mereka sering kali sulit menyesuaikan diri dalam kondisi sosial di mana terdapat konflik antara persepsi subjektif mengenai identitas gendernya dan kondisi fisik maupun identitas gender yang dilabelkan oleh orang lain. Hal ini dapat bermanifestasi menjadi keinginan untuk diperlakukan sebagai identitas gender yang ia inginkan maupun dorongan untuk menghilangkan karakteristik jenis kelamin yang dikaitkan pada identitas gender yang ditolaknya.
Proses Transisi Gender sebagai Bentuk Afirmasi
Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi tolak ukur diagnosis disforia gender. Seseorang harus menunjukkan perbedaan yang tampak jelas antara identitas gender yang ia rasakan secara personal dan identitas gender yang dilabelkan orang lain kepadanya. Orang tersebut akan merasa memiliki keinginan yang kuat untuk dianggap sebagai identitas gender yang lain. Hal tersebut seperti mengganti karakteristik identitas gender biologis dirinya yang sesuai dengan identitas gender yang ia inginkan.
Perbedaan ini dapat dianggap signifikan ketika berlanjut selama lebih dari 6 bulan. Bagi anak-anak, perlu ada pernyataan secara verbal atau ekspresif tentang keinginan untuk mengekspresikan diri sebagai identitas gender yang lain. Dengan berkembangnya zaman, penanganan keinginan kuat untuk mengubah gender ini oleh ahli tidak lagi dianggap sebagai permasalahan minor yang dapat diselesaikan dengan menyuruh orang dengan disforia gender untuk lebih banyak bergaul dengan komunitas identitas gender yang sama dengannya. Terdapat pendekatan baru yang lebih mengafirmasi identitas gender yang diekspresikan orang dengan disforia gender (Martin, Volkmar and Lewis, 2011). Apabila semua tolak ukur di atas sudah terpenuhi, rangkaian bentuk pengafirmasian identitas gender baru berupa transisi gender dapat dilaksanakan dalam lingkup medis.
Salah satu bentuk pengafirmasian dari keinginan kuat untuk mengganti identitas gender adalah dengan melakukan transisi biologis. Orang dengan dapat menjalani terapi hormon lintas seks (cross-sex hormone therapy) untuk menstimulasi perubahan karakteristik biologis melalui administrasi hormon ke dalam tubuh (Bracanović, 2017:88). Hormon yang diterima dibedakan sesuai dengan perubahan dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki. Pada transisi dari laki-laki ke perempuan, hormon yang diterima adalah estrogen dan pereduksi androgen untuk memunculkan perubahan seperti pertumbuhan payudara, pengecilan ukuran testis dan pengurangan fungsi ereksi, serta reduksi bulu tubuh. Sementara itu, pada transisi dari perempuan ke laki-laki, digunakan hormon testosteron untuk menstimulasi perubahan suara, pelebaran klitoris, pertumbuhan bulu wajah dan tubuh, penghentian haid, dan atropi pada jaringan payudara.
Selain itu, orang dengan disforia gender dapat direkomendasikan untuk menjalani operasi penggantian kelamin (sex reassignment surgery) apabila terapi hormon lintas seks dirasa kurang efektif. Operasi ini merupakan intervensi medis yang memodifikasi karakteristik fisik dan jenis kelamin orang dengan disforia gender sesuai dengan identitas gender yang ia alami secara subyektif (Bracanović, 2017:87). Sebelum dioperasi, orang
dengan disforia gender akan menjalani terapi hormon lintas seks terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan menjalani kehidupan secara 12 bulan dengan identitas gender yang kongruen. Tahap ini menjadi tantangan bagi seorang trans untuk menghadapi aspek sosial yang timbul saat seseorang mengganti identitas dan peran gendernya di masyarakat. Sebagai contoh, seorang trans akan menghadapi tantangan dalam ‘coming out’ atau memperkenalkan identitas gender barunya kepada keluarga, teman, dan anggota komunitas lainnya. Tahap operasi dapat dilakukan setelah kondisi medis dan psikologis dari orang dengan disforia gender diobservasi dan dianggap mungkin untuk dilakukan.
Terdapat dua tahap dalam operasi penggantian kelamin, di antaranya prosedur nongenital dan prosedur genital. Pada operasi laki-laki ke perempuan, prosedur nongenital dapat dilakukan melalui augmentasi payudara dan pantat, operasi feminisasi wajah, sedot lemak, pengangkatan jakun, dan rekonstruksi rambut. Sementara itu, prosedur genital dilakukan dengan pengangkatan atau pembuangan penis dan testikel serta pembuatan neovagina dan klitoris. Untuk operasi perempuan ke laki-laki, prosedur nongenital melibatkan pengangkatan payudara, rekonstruksi dada, sedot lemak dan terkadang operasi suara. Prosedur genital termasuk pengangkatan uterus, tuba fallopi, ovarium dan vagina, konstruksi penis dan skrotum serta implantasi prostesis testikular dan ereksi. Setelah melakukan operasi, maka orang trans dianggap telah melalui seluruh prosedur transisi biologis dalam penanganan disforia gender.
Sulitnya Mengupayakan Transisi Gender di Indonesia
Tentu saja definisi dan hal-hal prosedural mengenai disforia gender dan proses transisi gender di atas adalah berdasarkan pengalaman utopis, yang apabila dibandingkan dengan kondisi riil masyarakat Indonesia sangat jauh berbeda. Orang dengan disforia gender di Indonesia tidak memiliki keleluasaan yang sama untuk mengakses jaminan kesehatan (atau bahkan tindakan medis apapun) dalam keseharian mereka.
Di Indonesia, seseorang yang merasakan ketidaknyamanan pada alat kelamin biologis maupun norma gender yang sebenarnya tidak sesuai dengan identitas gendernya biasa disebut Waria (Sugano, Nemoto & Operario, 2006). Waria adalah panggilan dengan akar kultural yang panjang, berhubungan dengan asumsi gender dan seksualitas seseorang (Hegarty, 2017). Pengertian cerminan diri di kalangan waria umumnya digambarkan sebagai suatu
“keterputusan (antara tubuh laki-laki dan jiwa perempuan, antara keinginan memakai pakaian perempuan dan tubuh laki-laki).” (Boellstorff, 2007). Definisi ini memiliki kesamaan superfisial dengan fenomena tertulis ‘lahir dalam tubuh yang salah’ khas diskursus transgenderisme di Barat (Meyerowitz, 2002). Waria biasa bertingkah laku layaknya perempuan untuk menutupi sifat kelaki-lakian, seperti memakai pakaian perempuan, berdandan, mengubah gaya rambut seperti perempuan, dan mencukur bulu kaki.
Berbeda dengan orang dengan disforia gender yang dibicarakan di DSM-5, waria menghadapi banyak halangan untuk mengafirmasi gender yang mereka ekspresikan, karena akses untuk memperoleh fasilitas kesehatan di Indonesia seperti pengajuan untuk asuransi bagi pasien waria sangatlah sulit akibat banyak dari mereka yang tidak memiliki kartu identitas. Hal tersebut membuat waria mendapatkan penolakan saat ingin menggunakan fasilitas kesehatan. Pada akhirnya mereka menerima tindakan medis yang membahayakan, tanpa supervisi, dan bisa menyebabkan kematian. (Melendez, Bonem & Sember, 2006). Selain itu, masih banyak juga waria yang menghindari pelayanan kesehatan. Penghindaran ini didasari kesulitan untuk merasakan aman dan bebas dari diskriminasi medisi. Mereka merasa kesulitan untuk mengekspresikan apa yang mereka butuhkan kepada profesional kesehatan yang belum terlatih. Misalnya, ketika para waria ingin memeriksakan penyakit terkait aktivitas seksual. Mereka seringkali menghadapi sikap yang kurang ramah dan mendukung dari petugas kesehatan. Nasihat moral yang kurang bermanfaat bagi hidup mereka juga seringkali mereka dengarkan.
Perihal transgender, petugas kesehatan belum memiliki kesiapan untuk berbicara tentang jenis kelamin dan seksualitas kepada pasiennya, yang mana akhirnya membentuk stigma jika semua orang cisgender dan heteroseksual. Contohnya ketika pasien waria menyebutkan jika mereka ingin ditangani seperti layaknya perempuan, tetapi ahli kesehatan menolaknya karena merujuk pada jenis kelamin yang ada pada data kelahiran. Padahal, para waria telah memberitahu mereka jika mereka ingin ditangani sesuai dengan orientasi seksualnya. Penyedia layanan kesehatan juga belum terlalu familiar dengan fasilitas kesehatan apa yang dibutuhkan bagi waria (Feinberg, 2001).
Oleh karena keterbatasan-keterbatasan itu waria melakukan sendiri prosedur transisi gender tanpa pengawasan medis. Sebelum tahun 1970, waria mulai melakukan upaya agar mendapatkan hasil yang sama tanpa penanganan medis. Mereka meminum jamu dan meletakkan balon berisi air di bawah bra yang mereka pakai. Usaha waria untuk mencapai
imaji bentuk tubuh wanita yang sesungguhnya kemudian meningkat, mereka mulai meminum pil dan menyuntikkan kontrasepsi seiring dengan semakin tersedianya obat-obatan hormon di pasar. Suntikkan kontrasepsi diarahkan langsung ke paha, lengan, atau dada. Mereka menggunakan dosis suntikan kontrasepsi yang tinggi untuk menumbuhkan dada. Upaya untuk mempertahankan bentuk dada mereka lakukan dengan meminum pil kontrasepsi. Seiring waktu, peningkatan dosis pemakaian pil sering mereka lakukan hingga bisa mencapai 2-7 kali sehari dan dikombinasikan dengan suntikan kontrasepsi 1 kali seminggu.
Kulit yang lebih lembut, tumbuhnya buah dada, urat-urat yang memudar, massa otot yang berkurang, berkurangnya jerawat, dan wajah yang lebih glowing, menjadi efek yang menguntungkan, namun tidak luput pula dari efek samping. Rasa pusing, mual, kantuk, bintik merah di wajah, sembelit, diare, nyeri otot, dan rasa malas menjadi hal yang tak terhindarkan. Mereka juga biasanya terpaksa berhenti menggunakan produk dengan efek samping yang tidak bisa ditoleransi, seperti penambahan berat badan. Efek samping yang paling menyakitkan adalah ketika dada mulai tumbuh, dikarenakan kantung atau dasar bagi dada mulai terbentuk. Rasa sakit tersebut menjadi bukti bahwa transformasi besar di tubuh mereka sedang terjadi. Sebenarnya, mereka lebih menyukai implan silikon. Akan tetapi, pemasangan implan silikon membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Waria yang menumbuhkan dada, mendapatkan kehormatan dan legitimasi. Lain halnya dengan penggunaan padded bra yang hanya menjadi objek ejekan. Walaupun, tidak sedikit waria yang kembali memakai padded bra karena tidak tahan dengan efek samping saat menumbuhkan dada.
Upaya untuk mendapatkan tubuh yang feminim tidak berhenti sampai situ, mereka juga mendambakan kulit yang cerah. Asumsi jika kulit yang cerah lebih menarik daripada kulit gelap seringkali dikaitkan dengan feminitas.
Mencerahkan kulit akan lebih mendekatkan mereka dengan imaji ‘perempuan’ yang sebenarnya. Mereka percaya, jika pria lebih tertarik kepada perempuan yang memiliki kulit yang cerah. (Ashikari, 2005). Waria biasanya menggunakan produk eksfoliasi dan krim sebagai pemutih kulit mereka. Kemanjuran produk eksfoliasi seringkali mereka kaitkan dengan efek samping yang timbul, seperti kemerah-merahan, rasa perih, panas, dan kulit yang terbakar. Sedangkan untuk penggunaan krim harus digunakan secara terus menerus untuk mempertahankan kecerahan kulit mereka. Jika berhenti menggunakannya, maka kulit mereka bisa menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Perjuangan untuk menjadi terlihat feminim dan mempertahankannya memang harus mereka lalui dengan serangkaian proses yang menyakitkan bagi waria Indonesia.
Buruknya Penerimaan terhadap Orang dengan Gender Disforia
Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Terlahir dengan gender disforia, lalu dibesarkan dalam lingkungan yang masih menganggap transisi gender adalah suatu perbuatan yang salah. Kesadaran untuk tidak menjadikan konsep transgenderisme sebagai bahasan peyoratif masih minim. Transgenderisme dan homoseksualitas hampir tidak dianggap dan tidak ada nilainya (valorized) dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Masih banyak otoritas agama dan negara menganggap transgenderisme dan homoseksualitas sebagai kesalahan besar yang bertentangan dengan tradisi Indonesia. Tidak diterimanya transgender dalam masyarakat Indonesia adalah fakta yang memprihatinkan, mengingat sebenarnya disforia gender yang mereka rasakan adalah suatu pergolakan yang nyata. Menjadi trans tidak seharusnya mengakibatkan pengucilan dari masyarakat. Pengucilan, pengusiran, cacian, semua ini malah dapat memberikan efek negatif terhadap kejiwaan orang dengan disforia gender.
Orang dengan disforia gender tidak semestinya dicap sebagai orang yang memiliki masalah kejiwaan. Menjadi trans adalah normal, dan stres yang terjadi dapat diartikan sebagai hasil reaksi tubuh dibandingkan kejiwaan. Apabila seorang cisgender (non-transgender) bangun dan kemudian mendapati badannya berganti dengan badan yang tak semestinya ia punya, tentu ia akan stres. Dalam kasus cisgender, stres ini tak ayal tentu tidak langsung dilabeli orang banyak sebagai penyakit mental. Orang-orang tidak akan semena-mena melabeli stres itu sebagai penyakit mental, sebab ini adalah reaksi normal seseorang terhadap situasi yang atipikal. Analogi ini yang kemudian membuat jauh akan lebih masuk akal apabila menempatkan disforia gender sebagai permasalahan di badan. Kesimpulan ini juga ditarik dengan mempertimbangkan fakta bahwa pengobatan paling ampuh untuk disforia gender adalah melalui terapi hormon dan operasi, yang keduanya memang hanya bisa dilakukan ke fisik orang dengan disforia gender (Ashley, 2019).
Dari pengertian bahwa disforia gender adalah bukan penyakit kejiwaan, dapat pula ditambahkan bahwa orang dengan disforia gender malah cenderung rentan untuk mengidap gangguan kejiwaan. Hal ini disebabkan oleh lingkungan tidak sehat yang sulit menerima mereka. Gangguan kejiwaan adalah efek samping dari disforia gender. Gangguan kejiwaan hadir sebagai by product dari stigma dan stres yang hadir karena mereka adalah minoritas,
bukan karena mereka adalah trans (Askevis-Leherpeux, et. al., 2019). Gangguan kejiwaan ini muncul, menurut APA, karena stigmatisasi, diskriminasi, dan viktimisasi yang acap kali diasosiasikan dengan disforia gender. Ketiga hal ini berperan besar dalam citra diri yang negatif dan meningkatkan kemungkinan terjangkit gangguan kejiwaan yang lain. Individu trans lebih riskan terkena viktimisasi dan kejahatan kebencian (hate crime). Baik orang muda maupun tua pemilik disforia gender juga riskan memiliki tendensi untuk bunuh diri.
Anak-anak dengan disforia gender berisiko lebih tinggi mengalami masalah emosional dan perilaku dikarenakan merasa tertekan untuk berpakaian seperti jenis kelamin bawaan mereka, dan di saat yang sama turut mendapatkan ejekan dan pelecehan di sekolah. Masalah emosional dan perilaku tersebut seperti kecemasan dan depresi. Selain depresi, gangguan kejiwaan lain yang dialami oleh seorang pemilik disforia gender adalah skizofrenia, gangguan mood, gangguan makan, gangguan kecemasan, penyalahgunaan substansi, dan percobaan bunuh diri. Semua gangguan kejiwaan ini biasanya diidap oleh seseorang yang membiarkan disforia gendernya (untreated). Di sinilah pentingnya mendiagnosis dan melakukan perawatan yang tepat terhadap orang dengan disforia gender, untuk kemudian mencegah terjangkitnya mereka terhadap penyakit-penyakit mental di atas.
Lingkungan yang positif juga diperlukan untuk membangun rasa komunitas. Rasa komunitas akan mengakibatkan orang dengan disforia gender tidak merasa sendiri. Rasa komunitas ada untuk melawan stigmatisasi yang terjadi terhadap pemilik disforia gender. Seperti yang sudah dihimbau oleh The World Professional Association for Transgender Health dalam pernyataannya mengenai depatologisasi (berhenti melihat disforia gender sebagai gejala dari penyakit mental atau bahkan penyakit mental itu sendiri). Disforia gender merupakan satu dari berbagai fenomena yang mencerminkan keberagaman budaya manusia. Layaknya keberagaman budaya, seharusnya disforia gender dianggap lumrah dan tidak perlu dinilai sebagai penyakit.
Penulis: Alysia Noorma Dani, Marshanda Farah Noviana, Safira Tafani C.
Penyunting: Muhammad H. Wafi
Ilustrator: Prakasita Laras
Referensi
American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Arlington, VA: American Psychiatric Association.
Ashikari, M. 2005. Cultivating Japanese Whiteness, the ‘Whitening’ Cosmetics Boom and the Japanese Identity. Journal of Material Culture, 10, p. 73-91.
Ashley, Florence, 2019. The Misuse of Gender Dysphoria: Toward Greater Conceptual Clarity in Transgender Health. Perspectives on Psychological Science, p. 1-6.
Askevis-Leherpeux, F., de la Chenelière, M., Baleige, A., Chouchane, S., Martin, M., Robles-García, R., Fresán, A., Quach, A., Stona, A., Reed, G. and Roelandt, J., 2019. Why and how to support depsychiatrisation of adult transidentity in ICD-11: A French study. European Psychiatry, 59, p. 8-14.
Boellstorff, T. 2008. Playing Back the Nation: Waria, Indonesian Transvestites, Cultural Anthropology, 19 (2), p. 159-195.
Bracanović, Tomislav. 2017. ‘Sex Reassignment Surgery and Enhancement’. Journal of Medicine and Philosophy, 42 (1), p. 86–102.
Costa, A.B., Pase, P.F., Fontanari, A.M.V., Catelan, R., Mueller, A., Schwarz., et al. (2016). Healthcare Neecs of and Access Barriers for Brazilian Transgender and Gender Diverse People. Journal of Immigrant and Minority Health, p. 1-10.
Feinberg, L. 2001. Trans health crisis: For us it’s life or death. American Journal of Public Health, 91, p. 897-900.
Hegarty, B. 2017. ‘When I was transgender’: Visibility, subjectivity, and queer aging in Indonesia. Medicine Anthropology Theory , 4(2), p. 70.
Idrus, N.I. & Hymans, T.D. 2014. Balancing Benefits and Harm: Chemical Use and Bodily Tranformation Among Indonesia’s Transgender Waria. International Journal of Drug Policy, p. 789-797.
Liem, A. 2012. ‘Psikologi dan Waria, Ada Apa?’. Fakultas Psikologi. Universitas Ciputra. Surabaya.
Martin, A., Volkmar, F. and Lewis, M. 2011. Child And Adolescent Psychiatry. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
Melendez, R.M., Bonem, L.A., & Sember, R. 2006. On Bodies and Research: Transgender Issues in Health and HIV Research Articles. Sexuality Research & Social Policy: Journal of NSRC, 3(4), p. 21-38.
Sugano, E., Nemoto, T., & Operario, D. 2006. The Impact of Exposure to Transphobia on HIV Risks Behavior in a Sample of Transgendered Women of Color in San Fransisco. Aids and Behavior, 10 (2).