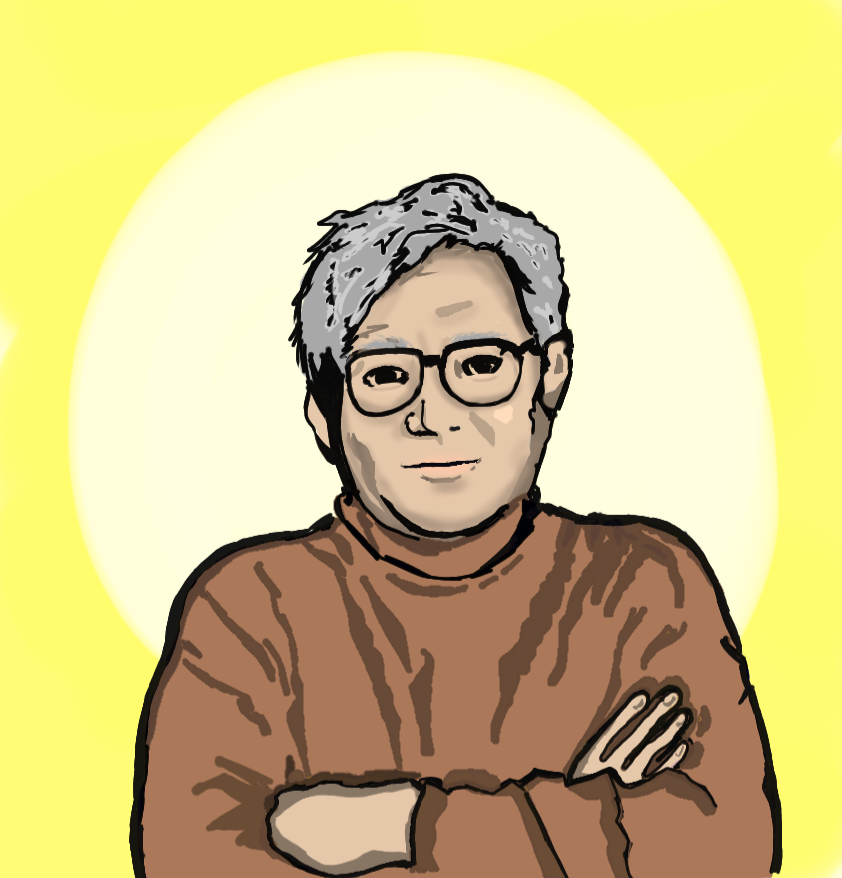
©Laras/Bal
Sempat populer di masa Orde Baru, wacana pers Pancasila seperti hilang dari pembahasan publik ketika rezim tersebut mengalami kejatuhan. Namun, pada Selasa (10-12), di Gedung Dewan Pers di Bilangan Kebon Sirih, Jakarta wacana tersebut hendak digulirkan kembali. Hari itu, Rektor UGM Panut Mulyono bertemu Muhammad Nuh selaku Ketua Dewan Pers. Pertemuan mereka tak lain adalah untuk menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan pers Pancasila di UGM. Langkah ini bagaikan petir di siang bolong lantaran belum jelas apa yang melatari kedua belah pihak untuk menggulirkan kembali wacana mengenai pers Pancasila.
Dalam rangka menjernihkan ingatan mengenai pers Pancasila, BALAIRUNG berkesempatan mewawancarai Andreas Harsono. Ia adalah mantan wartawan The Jakarta Post, pendiri Aliansi Jurnalis Independen, serta penerima Nieman Fellowship on Journalism dari Universitas Harvard. Andreas kini adalah peneliti di Human Rights Watch, sebuah LSM Internasional yang memantau dan mengadvokasikan hak asasi manusia. Berikut wawancara BALAIRUNG dengan Andreas Harsono mengenai pers Pancasila.
Wacana pers Pancasila pertama digulirkan pada rezim Presiden Soeharto, apa makna sebenarnya dari wacana tersebut?
Ya sebetulnya tidak ada maknanya. Menurut pemikir jurnalisme yang bermartabat di perguruan-perguruan tinggi ternama, pers Pancasila itu tidak berarti apapun. Konsep pers Pancasila tidak pernah terdengar di luar negeri. Media-media di New York, Paris, London atau Tokyo juga menganggapnya demikian. Pers Pancasila itu hasil pekerjaan orang yang tidak paham perdebatan dalam dunia jurnalisme.
Dalam jurnalisme dikenal yang namanya sepuluh elemen jurnalisme. Nah, kalau ada genre dalam jurnalisme biasanya genre itu menekankan pada salah satu dari sepuluh elemen itu. Misalnya jurnalisme investigasi yang dianggap sebagai salah satu genre jurnalisme karena penekanannya pada elemen jurnalisme sebagai pemantau kekuasaan. Contoh yang lain adalah jurnalisme sastrawi yang menekankan bahwa jurnalisme harus relevan dan memikat. Memikat artinya tulisan yang dihasilkan harus bermutu, sedangkan relevan artinya tulisan jurnalisme harus dengan penjelasan yang panjang lebar. Ada lagi genre jurnalisme yang disebut citizen reporting yang dikaitkan dengan elemen kesepuluh dimana warga punya tanggung jawab terhadap jurnalisme.
Sekarang pertanyaannya adalah pers Pancasila itu masuk elemen yang mana? Ya tidak ada. Sama halnya dengan konsep jurnalisme Islami, jurnalisme Pancasila itu mengada-ada. Keduanya itu teori yang dibuat oleh orang yang tidak ahli dalam jurnalisme. Teori semacam itu dalam bahasa Jawa disebut gothak-gathuk artinya terdengar bagus tapi tidak berarti.
Jika pers Pancasila tidak ada, lantas apa yang sebenarnya dijalankan pemerintah Orba waktu itu?
Waktu mingguan Detik, Editor, dan Tempo dibredel karena melaporkan dugaan korupsi pembelian kapal perang, pemerintah menggunakan pers Pancasila sebagai alasan pembredelan. Tapi ketika di pengadilan, pemerintah beralasan bahwa laporan itu tidak benar dan mengganggu stabilitas negara. Dari contoh ini, pers Pancasila itu hanya dipakai sebagai bualan saja. Buktinya, hakim pada kasus tersebut tidak menggunakan pers Pancasila sebagai argumentasi mereka.
Rektor UGM mengatakan pers Pancasila sekarang berbeda dari masa Orba karena pers mahasiswa diperbolehkan bersikap kritis. Apakah dengan kelonggaran tersebut lantas pers Pancasila hari ini berbeda dengan masa Orba?
Saya tidak tahu jawabannya karena saya tidak tahu apa keinginan Rektor UGM dan Ketua Dewan Pers sekarang. Pers Pancasila tidak pernah ada, baik di zaman Orba maupun zaman sekarang. Menurut saya mereka seperti tidak punya pekerjaan karena sesuatu yang dulu tidak pernah ada kok sekarang mau diadakan lagi oleh mereka.
Di masa Orba sebetulnya pers Pancasila tidak pernah ada. Fenomena yang ada adalah pembredelan pers menggunakan Pancasila. Pada tahun 1994 ketika mingguan Detik, Editor, dan Tempo dibredel saya kebetulan bekerja di The Jakarta Post dan saya merasakan langsung penyensoran pemerintah. Hampir setiap minggu ada saja telepon masuk untuk menyensor suatu pemberitaan. Saat itu di papan pengumuman redaksi sering ada imbauan untuk tidak memberitakan beberapa hal.
Apakah maksud Anda pembredelan adalah implikasi dari pers Pancasila?
Tidak, pembredelan bukan implikasi dari pers Pancasila. Saya membicarakan tentang sensor. Sebelum pers Pancasila, yaitu di masa Soekarno dan awal masa Soeharto, penyensoran sudah dilakukan. Intinya, pers Pancasila hanyalah stempel legitimasi yang diberikan pemerintah untuk melakukan penyensoran.
Apa implikasi pemberlakuan pers Pancasila terhadap kebebasan pers atau kebebasan berpendapat di kampus?
Kalau kerjasama antara UGM dan Dewan Pers hanya sebatas nota kesepahaman saya rasa tidak akan ada pengaruhnya. Apa yang disebut jurnalisme Pancasila itu adalah bentuk lain dari jurnalisme pembangunan. Wacana jurnalisme pembangunan masuk ke Indonesia melalui proyek yang diberikan CIA kepada dosen komunikasi di Universitas Indonesia, Alwi Dahlan. Dia menjadi Menteri Penerangan di akhir Orba. Tujuan proyek itu untuk membenarkan sensor di negara dunia ketiga yang menjadi sekutu Amerika Serikat (AS). Saat dipimpin oleh Soeharto, Indonesia adalah sekutu AS. Jadi, pers Pancasila itu sama halnya dengan propaganda. Pers Pancasila tidak kredibel.
Kemudian, apa motif yang membuat slogan pers Pancasila itu dapat muncul?
Saya tidak tahu. Anda harus bertanya kepada mereka yang menggulirkan kembali wacana ini. Mereka mungkin mengatakan ini adalah model pers yang mencerminkan ideologi Pancasila. Bagi saya Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila adalah kompromi politik yang dibuat pada 18 Agustus 1945 antara kelompok sekuler dan islamis. Hanya belakangan ini saja Pancasila dianggap sebagai sebuah ideologi.
Sebuah kompromi politik tidak berhubungan dengan genre jurnalisme. Bahkan kalau Pancasila dianggap ideologi sekalipun hubungan itu tetap tidak ada. Tidak pernah ada yang namanya pers komunis atau pers kapitalisme apalagi pers Pancasila. Pers Pancasila itu gothak-gathuk saja.
Ketika mereka mengatakan kalau pers Pancasila itu adalah pers yang mencerminkan Indonesia, saya tanya, Indonesia bagian mana yang dicerminkan dari pers Pancasila? Kita tidak bisa berasumsi jika Tempo dan Tirto mencerminkan Indonesia hanya karena mereka lokal atau New York Times tidak mencerminkan Indonesia karena mereka asing. Dari sini terlihat bila logika berpikir di balik perumusan pers Pancasila tidak karuan.
Apakah Anda pribadi setuju dengan pemberlakuan pers Pancasila?
Persoalannya bukan setuju atau tidak, pers Pancasila itu tidak ada.
Bagaimana seharusnya jurnalis di level kampus menyikapi pemberlakuan kembali pers Pancasila ini?
Pers kampus tetap jalan seperti biasa saja. Anda tetap saja bikin liputan yang bermutu dan mengikuti prinsip jurnalistik yang ada. Prinsip-prinsip itu seperti cover both sides, verifikasi, transparan, jujur, tahu urutan sumber, berpikir terbuka, dan gunakan pertanyaan terbuka. Pers Pancasila itu diabaikan saja. Anda pakai saja fasilitas dan biaya yang ada dari pemberlakuan pers Pancasila untuk kongko atau buat diskusi yang berguna.
Erata: penulisan “pancasila” diubah menjadi “Pancasila”, “jurnalisme islami” menjadi “jurnalisme Islami”, dan “majalah Tempo, DeTik, dan Editor” menjadi “mingguan Detik, Editor, dan Tempo”.
Penulis: Hanif Janitra
Penyunting: Ayu Nurfaizah
Ilustrator: Prakasita Laras