
©Arsip/BAL
Mengakhiri peringatan peristiwa Gerakan 30 September (G30S), BALAIRUNG kembali mengunggah arsip mengenai dinamika politik dan hukum pada saat itu dan setelahnya. Pada kesempatan ini, BALAIRUNG membahas tahanan politik Orde Lama dan Orde Baru, hingga upaya rekonsiliasi nasional. Artikel ini dimuat Majalah BALAIRUNG NO. 22/TH.IX/1995 dalam rubrik Berita Tema yang mengulas tema-tema tertentu. Demi keterbacaan artikel, kami melakukan penyuntingan minor yang meliputi diksi dan bahasa sebelum mengunggah di laman ini. Berikut adalah artikelnya.
Di seputar tahun 1960-an ketika usia sudah mencapai kepala enam, konon Presiden Soekarno dihinggapi rasa cemas. Ia merasa revolusi Indonesia stagnan. Padahal revolusi yang berkobar pada 17 Agustus 1945 belumlah selesai. Revolusi harus berjalan terus selama tujuannya belum tercapai.
Namun, Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 1959 untuk mengakhiri tidak beresnya politisi dalam mempraktikkan demokrasi liberal juga tidak menolong. Bahkan, dekrit menimbulkan kevakuman politik. Saat itulah, pada 22 Juli 1959 untuk pertama kalinya, Indonesia mempunyai peraturan hukum bernama Penetapan Presiden (Penpres) yang mengatur segera dibentuknya DPR sebagai pengganti konstituante.
Penpres dianggap sebagai hukum revolusi tidak lama setelah muncul konsep demokrasi dan ekonomi terpimpin. Keluarlah PNPS No. 11/1063 yang terkenal sebagai Undang-Undang Subversi. Produk hukum ini sengaja diciptakan sebagai alat untuk menghalalkan segala cara mencapai tujuan revolusi sebagai cara menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Jadi, setiap orang yang tidak menghendaki susunan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan ajaran Manipol dengan demokrasi terpimpinnya. Maka, menurut Penpres ini, mereka digolongkan pada anasir-anasir subversi yang dapat dikenakan tindak pidana subversi.
Uniknya, Penpres produk Orde Lama itu akhirnya dioper dan dipakai oleh pemerintah Orde Baru. Padahal, berdasarkan TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945, produk berbentuk Penpres itu harus ditinjau kembali. Penpres itu tidak dicabut, karena bagi Orde Baru ternyata Penpres itu berguna sebagai alat untuk menjatuhkan sisa-sisa pelaku G30S/PKI. Sejarah membuktikan bahwa Penpres itu akhirnya memangsa banyak korban, bukan hanya PKI, tetapi juga dari kalangan Islam atau gerakan separatis. Pada masa Orde Baru, tahanan politik atau narapidana politik menjadi istilah yang sering dipakai untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya.
Menurut Prof. Dr. Ichlasul Amal, istilah Tapol-Napol itu khas Orde Baru. “Di masa Orde Lama, Mochtar Lubis atau Natsir pernah ditahan Soekarno, tetapi mereka tidak disebut sebagai Tapol-Napol. Tidak ada batasan yang jelas dan kriteria yang pasti seseorang disebut Tapol-Napol.” Ujar Staf pengajar Fisipol UGM ini lebih lanjut melihat kontradiksi dari batasan Tapol-Napol. “Pengadilan pidana politik itu sebenarnya tidak ada. Pengadilan hanya mengadili perkara kriminal. Keyakinan politik itu sendiri tidak dapat diadili. Tetapi, kalau keyakinan itu diwujudkan dalam suatu tindakan yang merusak, maka tuduhan itu yang harus diadili,” tambahnya.
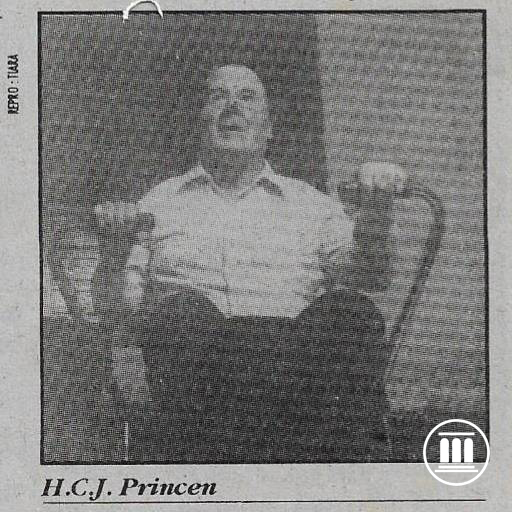
©Arsip/BAL
H.J.C. Princen bahkan menilai konstitusi Indonesia bukan hanya melindungi keyakinan politik, tetapi juga tindakan politik sepanjang tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. “Jika seseorang ditahan atau dihukum karena tindakan politiknya, itu lebih karena sifat tindakan itu, misalnya ia menggunakan kekerasan hendak membunuh presiden, dan bukan karena hakekat keyakinan politiknya,” ujar Princen. Maka, bagi direktur Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi ini, istilah Tapol-Napol sebenarnya tidak dikenal dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Setiap negara, lanjut Princen, memang berhak menjaga dirinya dari usaha-usaha yang bermaksud untuk meruntuhkan negara serta menjajah negara dan bangsa. Oleh karena itu, adalah wajar apabila negara membuat seperangkat aturan yang bersifat preventif dan represif mengenai bahaya yang mengancam kelangsungan hidupnya. Tetapi, hadir permasalahan terkait dengan aturan-aturan yang mengekang demokrasi dan hak asasi manusia. “Nyatanya di Indonesia kekuasaan negara sedemikian besarnya, dan dapat memaksakan kehendaknya sehingga menghambat demokrasi,” tambahnya.
Sistem Politik Orde Baru
Fenomena kemunculan Tapol-Napol sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem politik Orde Baru secara keseluruhan. Meskipun PKI dan para pendukungnya berhasil disingkirkan setelah kegagalan perebutan kekuasaan oleh G30S/PKI, namun kekhawatiran akan terjadinya konflik politik yang tajam masih tetap saja ada. Hal yang paling dikhawatirkan oleh pemimpin Orde Baru adalah munculnya konflik-konflik “ideologis” seperti masa sebelumnya, terutama yang berasal dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Setiap orang atau golongan yang tidak mematuhi aturan yang telah digariskan dapat dijadikan sebagai tahanan/narapidana politik.
Sampai tahun 1970-an, isu yang paling menonjol adalah mengenai PKI. Menurut catatan Amnesti Internasional, sebanyak 1.014 orang yang sempat ditahan berkenaan dengan G30S/PKI. Dari jumlah itu, hampir separuh telah dijatuhi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman 20 tahun. Dari 400 perkara yang telah diputuskan di pengadilan, kira-kira 150 orang telah dijatuhi hukuman mati. Data terakhir menunjukan bahwa jumlah yang sudah dihukum mati sebanyak 67 orang. Dari jumlah itu yang sudah dieksekusi sebanyak 18 orang, yang telah diubah –menjadi seumur hidup, 20 tahun atau dibebaskan– sebanyak 3 orang. Sehingga yang tersisa dan menunggu perkembangan ada 46 orang.
Menjelang tahun 1980-an, muncul Tapol dari kalangan Islam. Kemunculan Tapol ini tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran pemimpin Orde Baru akan kemunculan kelompok-kelompok Islam radikal. Kelompok ini dicurigai menggunakan sentimen agama sebagai daya tarik dalam menuntut berbagai hal yang menonjolkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat mengganggu pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Masa-masa ini adalah masa rekayasa besar-besaran terhadap organisasi masa dan kelompok Islam yang menyebabkan letupan-letupan dalam masyarakat. Buktinya, muncul penentangan yang kemudian disertai dengan penangkapan dan penahanan. Menurut catatan Panjimas, secara acak sejak 1985 sampai 1987, tercatat 180 narapidana politik Islam terpuruk di dalam ruang sempit sel penjara.
Mulai dari Usroh, Darul Islam, Tanjung Priok, Komando Jihad, Penyebaran selebaran gelap, LP3K, khotbah, mencuri bahan peledak, peledakan gedung BCA, Talang Sari Lampung, dan berbagai kasus lain. Selain yang telah dibebaskan, kini sekitar 30 orang masih meringkuk di lembaga permasyarakatan dengan masa tahanan –sebagian– seumur hidup untuk mereka yang berunsur komando jihad dan sebagian lagi antara 18 tahun hingga 20 tahun bagi mereka yang gerakannya dikenal komando jihad, Lampung, GPK Aceh, dan aksi bom bis Pemuda di Malang.
Selain Tapol dari G30S/PKI dan Islam, banyak Tapol juga berasal dari gerakan separatis. Dari catatan Amnesty Internasional, ada 80-an orang yang ditahan. Mulai dari Gerakan Aceh Merdeka sebanyak 24 orang yang rata-rata dipenjara seumur hidup, 20 tahun sampai 6 tahun, Gerakan Papua Merdeka sebanyak 16 orang yang kebanyakan seumur hidup dan penjara 6 tahun hingga 12 tahun. Sedang lainnya dari Gerakan Timor Timur Fretilin. Akhir-akhir ini justru muncul Tapol jenis baru yang berasal dari mahasiswa, aktivis hak asasi manusia, gerakan pro demokrasi ataupun gerakan buruh.
Secara keseluruhan, menurut data yang diperoleh BALAIRUNG dari Yayasan Penghayat Keadilan, ada 263 tahanan politik di seluruh Indonesia. Angka ini belum termasuk yang ditahan di berbagai rumah tahanan militer di Irian Jaya, Timor Timur, Aceh, dan Lampung. Dari jumlah itu sebagian diantaranya telah berusia lanjut dan sakit-sakitan.
Hegemoni Negara
Tapol-Napol berbeda dengan tahanan/narapidana perkara kriminal biasa. Hal ini dikarenakan kasusnya adalah politik, maka dasar yang membuat mereka ditahan atau dipidana tidak dapat dilepaskan dari alasan-alasan politis tertentu. Selama ini yang dituduhkan kepada mereka adalah mereka hendak menggulingkan pemerintah yang sah atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Dari mantan Tapol-napol yang berhasil dihubungi BALAIRUNG seperti Oei Tjoe Tat, Pramoedya Ananta Toer, HCJ Princen, Oemar Dhani, A.M. Fatwa, H.M. Sanusi –kesemuanya menolak tuduhan itu.
A.M. Fatwa misalnya mengingatkan agar dalam menilai Tapol Islam harus dikaitkan dengan peristiwa politik yang melingkupinya waktu itu. Peristiwa politik masa itu, menurut Fatwa, memang menyudutkan kepentingan muslim. Dan hal-hal itu yang melahirkan keberanian menentang (lihat: Seputar Tapol Islam).
Pramoedya bahkan lebih pedas, menilai bahwa para Tapol itu dijebloskan ke penjara kebanyakan tanpa melalui suatu proses pengadilan. “Saya sendiri mengalaminya. Ditahan selama 14 tahun. Sampai sekarang tidak ada tuduhan dan pengadilan apa-apa bagi saya. Salah saya apa? Tahu-tahu saya diambil lalu dipenjara,” ujarnya. Bagi Pram, keadaan waktu itu memang diwarnai oleh pertentangan ideologi yang tajam dan saling berhadap-hadapan. “Saya dituduh LEKRA, padahal di LEKRA saya hanya anggota kehormatan. Saya bukan orang organisasi. Terus mengenai realisme sosialis dapat saya jelaskan begini. Saya sebetulnya tidak tahu banyak. Waktu itu saya disuruh berbicara di Universitas Indonesia tentang realisme sosialis. Dari literatur di perpustakaan saya, saya susun makalah mengenai hal itu. Saya hanya menulis makalah, karena memang diminta berbicara mengenai hal itu. Lantas orang lalu menuding saya menyebarkan ajaran realisme sosialis. Itu bukan garis LEKRA,” tambahnya.
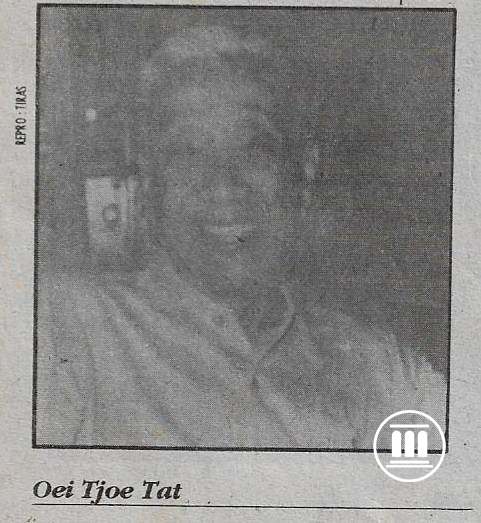
©Arsip/BAL
Oei Tjoe Tat, bekas menteri dalam pemerintahan Soekarno, yang ditahan karena dituduh melakukan kup terhadap Soekarno, bahkan balik bertanya. “Siapa pun tahu bahwa saya dikenal sebagai salah satu pengikutnya, sebagai fellow travellernya yang setia. Lantas sungguh aneh kalau kemudian saya dituduh subversif terhadap pemerintah Soekarno dimana saya termasuk salah seorang anggota kabinetnya. Apakah dengan ini yang mau dicapai adalah mendiskreditkan Soekarno, dimana saya termasuk pengikutnya? Rasanya terlalu janggal pula.” Bagi Oei Tjoe Tat, yang justru lebih menggelisahkan adalah nasib ribuan orang yang ditahan, lalu dibuang ke Pulau Buru. Padahal mereka tidak tahu menahu tentang politik pada masa itu.
Selama ini negara yang menafsirkan sejauh mana seseorang terlibat dalam tindakan subversi. Dalam kasus Tapol-Napol separatis, selama ini orang dituduh gerakan makar adalah mereka orang-orang yang dituduh hendak melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Pemerintah sama sekali tidak disinggung kesalahannya yang menyebabkan timbulnya gerakan atau tindakan semacam itu. Collin Mc. Andreas, lewat bukunya Central Government and Local Development in Indonesia (1986) misalnya, melihat kemunculan gerakan separatis itu sebagai letupan perasaan tidak puas terhadap pemerintah. “Janji-jani kemakmuran tidak juga muncul. Apalagi adanya jurang yang lebar antara daerah dan pusat atau kebijakan yang merugikan daerah. Hal ini menyebabkan kekecewaan yang berpuncak pada gerakan radikalisasi. Maka penanganan gerakan ini jangan hanya melihat kebijakan-kebijakan yang selama ini turut menciptakan ketegangan,” tulis Mc. Andreas.
Trauma Nasional
Tragedi politik 1965, demikian juga peristiwa Lampung, Tanjung Priok, GPK Aceh, Timor Timur telah menoreh “luka” yang mendalam bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Garis persaudaraan, kekerabatan, pertetanggaan, pertemanan acapkali renggang karena perbedaan politik. Bahkan dampaknya terus membekas hingga kini, bukan hanya pada mantan Tapol/napol saja, tetapi juga pada keturunan mereka. Bahkan isu ini terus-menerus diperkuat oleh penguasa. Misalnya, lewat kebijakan litsus (Penelitian Khusus) dan keterpengaruhan yang digunakan untuk meneliti sejauh mana seorang warga negara, terutama keturunan mantan Tapol/Napol bersih secara ideologis. Hal ini terjadi ketika mereka hendak menjadi pegawai negeri, tentara dan anggota parlemen. Keturunan mantan Tapol/Napol ini dicurigai hanya karena lingkungan atau kerabatnya pernah terlibat kegiatan politik yang berlawanan dengan pemerintah. Sedangkan hukum yang berlaku secara jelas dan tegas menyatakan pidana hanya bisa dikenakan pada si pelaku.
Oemar Dhani yang pernah ditahan karena terlibat G30S/PKI kepada BALAIRUNG mengungkapkan efek penahanannya pada kehidupan keluarganya. “Anak saya mau masuk pegawai negeri susah. Bahkan untuk pacaran saja susah. Anak saya (sembari menunjuk anak laki-lakinya) putus pacaran gara-gara mertuanya malu, bapaknya pernah terlibat PKI. Ya sepertinya kita ini kok harus selalu dikasihani,” ujarnya. Oemar Dhani tidak sendirian. Banyak kasus dapat disebut. Seperti surat pembaca DeTIK (No. 30/5 Oktober 1993) tentang pernikahan dengan calon suami seorang ABRI yang gagal. Setelah pihak suami mengetahui calon istrinya anak seorang eks Tapol, pernikahan tersebut lantas dibatalkan.
Pengalaman traumatik kita dengan Peristiwa Tanjung Priok, Madiun, DI/TII, PRRI/Permesta, Peristiwa Dili dan sebagainya, terus menerus dihidupkan lewat memori. Para pejabat selalu melontarkan “bahaya komunisme” atau “bahaya fundamentalisme Islam” dalam retorika politiknya. Bahwa komunisme/fundamentalisme masih kuat, oleh karena itu harus diwaspadai sebagai bahaya laten. Kekejaman komunis PKI, radikalisme Islam juga selalu diulang-ulang supaya orang tidak melupakannya. Namun, sangat disayangkan kekejaman lain terus berlangsung, seolah bukan peristiwa yang patut diperhatikan seperti penggusuran hak-hak buruh dan sebagainya.
Tentang reproduksi bahaya yang terus menerus ini, Princen mempunyai komentar yang menarik. “Apakah rakyat Indonesia menderita amnesia sejarah, sehingga setiap waktu terus-menerus harus diingatkan? Padahal dengan terus memupuk dendam dan membuat sebagian anggota masyarakat larut dihimpit rasa bersalah, rendah diri dan akhirnya tidak dapat mengembangkan diri secara wajar,” ungkap Princen.
Rekonsiliasi Nasional?
Pertanyaan kemudian, mungkinkah dilakukan rekonsiliasi nasional, dengan memberi hadiah amnesti kepada para tahanan politik? Princen, secara tegas menghendaki terjadinya rekonsiliasi, dimana sudah waktunya pemimpin sekarang memaafkan “dosa-dosa politik” para lawan politiknya.
Sebagai bangsa yang berprikemanusiaan sudah seharusnya memberi hukuman yang tidak melewati batas ketahanan seseorang. Berikanlah kesempatan kepada mereka untuk meninggal tenah di rumahnya sendiri dan dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai,” tuturnya.
Tetapi bagi Ismail Hasan Mataerum, isu rekonsiliasi terhadap para Tapol napol itu dinilai sebagai salah alamat. Menurut wakil ketua DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini, tidak perlu ada rekonsiliasi, sebab tidak ada perpecahan. “Rekonsiliasi antara siapa dengan siapa. Yang benar adalah sikap maaf-memaafkan. Namanya silaturahmi. Jangan samakan dengan Tapol. Ujungnya silaturahmi antara individu dengan individu,” tambahnya.

©Arsip/BAL
Brigjend. Roekmini Koesoema Astuti punya pandangan lain. Bagi anggota komisi Komnas HAM ini, rekonsiliasi terhadap para Tapol/napol tidak penting, yang justru lebih mendesak adalah pembenahan terhadap sistem politik. “Adanya Tapol/napol itu karena mereka mau mengubah sistem Pancasila. Padahal, Pancasila yang kita anut itu sudah sempurna. Kalau sekarang ada penyimpangan bukan sistemnya yang salah tetapi mekanisme dan orang-orangnya yang salah,” katanya. Karenanya, lanjut Roekmini, mekanisme itu harus dibetulkan, bukan dengan mengganti sistemnya.
Dari perspektif politik, pembebasan Tapol-napol, jelas merujuk kepada pemberian amnesti. Di Indonesia ada pengampunan dari presiden untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap sekelompok orang yang terlibat peristiwa pidana. Jadi segala tuntutan terhadap kelompok orang itu dihapuskan, yang didasarkan kepada kebijaksanaan pemerintah atau presiden sebagai pemilik hak prerogatif.
Dalam seminar mengenai Tapol yang diselenggarakan oleh MIK (Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan), Marzuki Darusman, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan kesulitan pemberian amnesti ini. Menurutnya pemberian amnesti bertalian erat dengan suatu tujuan untuk menciptakan kondisi politik baru. Undang-undang tentang amnesti dan abolisi tahun 1954 juga menegaskan bahwa hal ini dapat dilakukan presiden atas dasar kepentingan negara. Pertanyaannya, atas dasar kepentingan negara yang bagaimana pada saat ini sehingga anjuran amnesti dianggap perlu diberikan? Dengan demikian pemberian amnesti sukar dilakukan karena mengandung konsekuensi pertanggungjawaban politik oleh presiden.
Marzuki Darusman mengusulkan amnesti dapat diberikan kepada napol yang tidak secara langsung bertanggung jawab atas timbulnya perbuatan tindak pidana keji yang berlatar belakang situasi dan kondisi politik tertentu. Pembebasan dengan cara lain adalah atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Secara hukum, cara seperti ini tidak dilakukan melalui amnesti, melainkan dengan grasi dan perlakuan secara khusus. Hal ini yang telah diperjuangkan oleh banyak kalangan.
Ditulis ulang dengan penyuntingan oleh Beby Pane dan Harits Naufal Arrazie