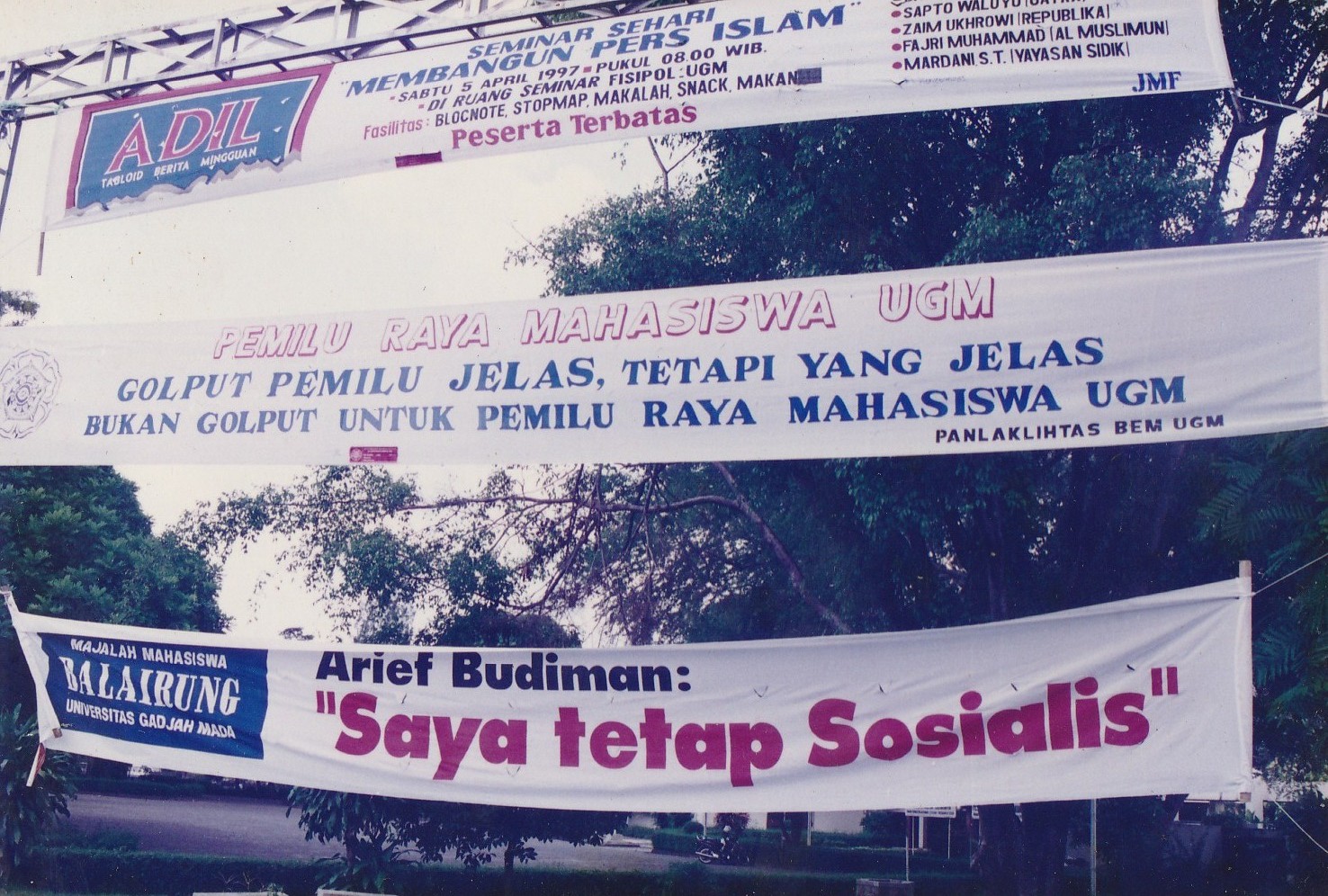Problem Kesekarangan dan Tawaran Masa Depan
Demonstrasi 2 Mei 2016 merupakan bukti telak bahwa gerakan mahasiswa UGM terjebak pada perulangan yang sama. Aksi yang sempat membuat para aktivis mahasiswa berbangga hati itu—setidaknya bangga dalam hal kuantitas massa yang berhasil dihimpun—melupakan strategi “meregenerasi” massa agar selalu mewacanakan isu bersama. Apa yang ingin saya tekankan yakni di sini lah internal gerakan tengah “gagap” dan terlalu terburu-buru dalam melakukan aksi tanpa strategi untuk memperpanjang umur gerakan. Mutlak, agenda tuntutan pun tak terjawab, dibungkam lewat ruang diplomasi elitis ala pejabat rektorat dan sibuk melayani wawancara stasiun televisi ternama.
Belajar dari demonstrasi itu pula, agaknya kita harus insyaf bahwa aksi yang berangkat dari “sentimen” tidak akan bertahan lama jika tidak dibarengi dengan rasionalisasi atas sentimen tersebut. Tidak bisa dipungkiri, titik ledak demontrasi 2 Mei berangkat dari sentimen atas pernyataan rektor yang telah berbohong kepada publik. Momentum itulah yang kemudian dijadikan alasan untuk memperkuat barisan massa yang datang dari berbagai macam isu. Bukan pada sebuah isu yang kemudian menciptakan momen bersama. Tepat di sini lah rasionalitas tersebut diletakkan, yaitu bagaimana memposisikan isu (yang dianggap momennya telah selesai) bisa tetap menciptakan momen dan/atau aksi bersama di kemudian hari.
Pelan tapi pasti, gerakan mahasiswa tengah menggali kuburannya sendiri. Ia tidak lagi sadar akan posisi kelasnya yang berada di antara dua tegangan (kelas atas dan kelas bawah). Gerakan tidak lagi berani berselingkuh dengan militerisme seperti yang terjadi pada angkatan 66, tidak lagi berani memperkuat kedekatan dengan gerakan masyarakat sipil seperti yang terjadi pada angkatan 98. Dalam strategi pergerakan, langkah ini diperlukan untuk menciptakan social-supporting-sytem yang berguna untuk memperkuat sekaligus melindungi gerakan. Mau tidak mau, gerakan mahasiswa haruslah melakukan pembacaan terhadap bagaimana fenomena kelas “kemahasiswaan” hari ini, akan kemana gerakan mahasiswa tersebut diarahkan, juga metode apa yang paling tepat untuk bergerak di tengah zaman yang telah berganti.
Di sisi lain, satu hal krusial tapi kerapkali luput dalam membaca fenomena gerakan mahasiswa adalah adanya perubahan orientasi institusi pendidikan dari kampus perubahan menjadi perubahan kampus. Gedung tinggi dibangun, jaminan akreditasi internasional, dan lapangan GSP telah berhasil disulap menjadi tempat parkir mobil mahasiswa! Kondisi ini berawal dari penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum. Seluruh perguruan tinggi berhak untuk mengelola keuangannya sendiri, dan memisahkan hartanya dari kekayaan Negara. Celah ini lah yang menjadi pintu masuk institusi pendidikan untuk menaikkan biaya kuliah. UGM sampai sekarang masih berstatus PT BHMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013. Perubahan kampus pada kenyataannya membuat gerakan mahasiswa terlena dengan segala “kenyamanan” yang telah dijanjikan pihak kampus.
Perubahan atas orientasi institusi pendidikan hanya bisa dimungkinkan terjadi ketika setiap organ gerakan (kemahasiswaan) telah selesai dengan persoalan “kegagapan” yang berada di dalam tubuhnya. Layaknya dengan apa yang terjadi pada politik representasi “KM-UGM” memunculkan segolongan elit mahasiswa yang dianggap “merepresentasikan” golongan yang kita sebut sebagai “massa”. Sialnya, elit mahasiswa memandang bahwa perubahan yang baik hanya bisa ditempuh lewat pergantian struktur, melupakan basis massa yang perlu mereka libatkan. Hal tersebut membuang jauh persoalan “partisipasi” yang sebenarnya amat dibutuhkan dalam menggaungkan suatu ideologi gerakan. Partisipasi di sini tidak hanya diartikan sebagai keterlibatan massa dalam mengawal agenda politik gerakan, akan tetapi juga pada proses dialektika antar generasi yang memungkinkan gagasan politik kebersamaan dapat selalu dibicarakan sekaligus diperbarui. Sebab, bila mengandaikan partisipasi tetapi masih memberangkatkan dirinya pada representasi “berbatas” (ruang dan waktu tertentu) hanya mengantarkan kita pada proses pengandaian yang sia-sia belaka.
Auviar Rizky Wicaksanti (Ghembrang)
Seorang Penghuni Ruang Gelap yang hanya berteman dengan teks, teh dan alunan musik Portishead.