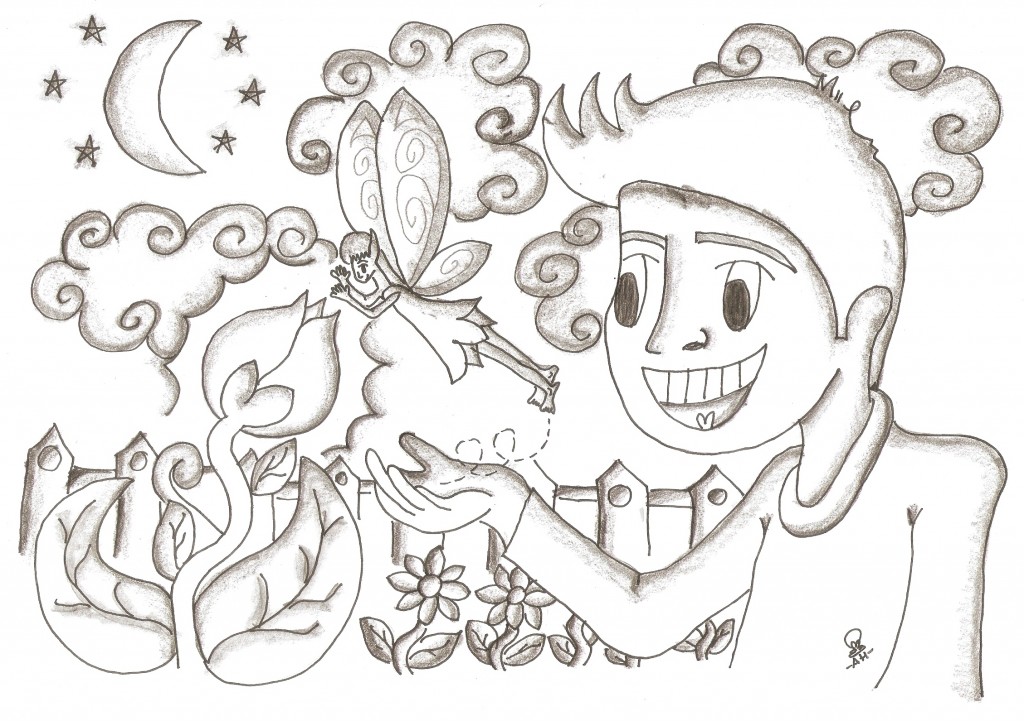
©Hanin.bal
AWALNYA aku masih tidak percaya. Peri-peri sawah berkeliaran di malam hari. Melantunkan sajak-sajak diiringi alunan merdu suara angin. Mereka menari. Langkah-langkah mungil itu beriak riang di atas dedaunan dan bunga padi.
Iya! Bibi Elisa seorang penulis yang hebat. Imajinasinya begitu luar biasa. Orang-orang selalu menggambarkan kebobrokan negeri ini. Namun, ia justru bisa melukiskan keindahan negeri ini layaknya surga yang sengaja dijatuhkan dari langit. Termasuk ceritanya tentang peri-peri sawah.
Waktu itu aku menyengajakan diri menginap di rumah Bibi Elisa. Kata ‘sengaja’ aku pilih karena orang-orang memang tak mau menyempatkan diri menengok Bibi Elisa, termasuk kedua orang tuaku. Dengan berbagai macam alasan, semua anggota keluarga tak mau berkunjung ke rumah Bibi Elisa. Salah satu alasan yang paling sering kudengar adalah rumah Bibi Elisa terlalu pelosok. “Ndeso,” ucap mereka diikuti gerak bibir mengkerut seperti pantat ayam.
Bahkan, Nenek pun sering mencibir cara hidup Bibi Elisa. Aku selalu mendengar keluhan Nenek di malam hari. Ditemani siaran stasiun televisi swasta, kami mengobrol santai di ruang tengah. Aku, Nenek, Ayah, dan Ibu.
“Nenek tak pernah bisa mengerti pikiran Bibimu. Sejak kecil tinggal di daerah kota. Tuanya malah menghabiskan hasil kerjanya buat beli tanah di desa. Mana jauh pula tempatnya,” gerutu Nenek.
“Padahal Ibumu yang sedari kecil tinggal di desa, tuanya lebih suka tinggal di kota. Jarang-jarang Ibumu mau pulang kampung,” tambah Ayah.
Ibu memanyunkan bibirnya seraya berkata, “Orang pintar memang suka aneh-aneh pikirannya”.
Aku hanya mendengarkan saja obrolan di antara mereka. Jemariku sibuk menekan tombol angka di remote televisi secara bergantian. Yang ada hanyalah sinetron remaja kota dan reality show yang penuh dengan tawa dan hingar bingar.
Tanpa sadar hatiku berseru menanggapi obrolan mereka. Aku tetap suka pergi ke rumah Bibi Elisa, seru hati kecilku. Menghabiskan liburan sebulan penuh di rumah Bibi Elisa pun aku jalani dengan suka hati. Semua itu aku lakukan bukan karena Bibi Elisalah yang menanggung semua biaya pendidikanku hingga bangku kuliah. Bukan itu alasannya. Bibi Elisa jauh lebih berharga dibanding alasan itu. Mengunjungi Bibi Elisa itu bisa kukatakan seperti berkunjung ke negeri dongeng.
Laiknya Hansel yang pergi ke hutan dan menemukan rumah kue yang cantik dan lezat. Itulah yang aku rasakan saat berkunjung ke rumah Bibi Elisa. Perjalanan jauh menuju rumah Bibi Elisa akan langsung terbayar saat memasuki rumah dengan latar halaman depan penuh tanaman bunga.
Di antara hamparan tanaman bunga, tampak sebuah dangau. Sengaja Bibi Elisa membangun dangau buatan itu di tengah kolam ikan. Di sana Bibi Elisa lebih sering menghabiskan waktunya untuk menulis cerita atau sekadar melepas lelah usai pulang dari mengajar di universitas. Bibi Elisa ketat membagi waktu. Dia hanya mau mengajar dari hari Senin hingga Rabu. Sisa hari lainnya dia habiskan di rumah pelosoknya itu.
Menghabiskan hari di rumah pelosok bukanlah hal yang mudah bagi semua orang. Tak ada kafe ataupun mal yang bisa dikunjungi. Sinyal internet pun tak terlalu bagus untuk beberapa provider. Tapi bukan berarti kebahagiaan sama sekali tak dapat ditemukan di tempat pelosok.
Setiap pagi Bibi Elisa bersepeda berkeliling desa. Hawa dingin di pagi hari terasa begitu menyengat sekaligus menyegarkan. Semua beban-beban di otak hilang terbawa hembusan dingin angin pagi. Saat menatap ufuk timur tampak sorotan mentari pagi keluar dari persembunyiannya. Warna kuning keemasan menyibak gelap langit fajar.
Tatkala matahari mulai meninggi, perempuan berusia hampir 40 tahun itu menyambangi hewan-hewan ternaknya. Makhluk peloncat bertelinga panjang itu berjejeran di depan pintu kandang. Mereka tak sabar menunggu sayuran hijau segar untuk menu sarapan. Di blok lainnya si pekokok sudah ramai menanti bekatul. Kokok mereka semakin kencang saat melihat Bibi Elisa semakin mendekat. Seolah-olah mereka berteriak, “Tuan, ke mana saja? Saya sudah tidak sabar menyantap sarapan pagi ini. Mulut ini tak sabar meremas-remas bekatul-bekatul lezatmu”.
Menyenangkan sekali mengikuti Bibi Elisa mengurusi hewan-hewan ternaknya. Tak ada yang menyangka, perempuan yang sedari kecil hobi tidur sambil membaca buku, suka beternak. Dia merawat hewan-hewan ternaknya seperti merawat anak-anak kandungnya sendiri. Curahan kasih sayang terpancar jelas dari tiap tawa dan gerutu mungilnya.
Sore harinya Bibi Elisa pergi menyambangi sawah dan tegalannya. Dipandanginya makanan bahan pokok yang sedang tumbuh menua. Bola mata coklatnya bersinar terang terkena bias sinar matahari senja.
“Semakin mereka tua, semakin mereka berguna. Harapan hidup semua penduduk bergantung pada mereka. Betapa mereka sangat berarti,” gumam bibir tipisnya.
Bibi Elisa akan duduk hingga adzan maghrib terdengar sayup-sayup di telinganya. Aku selalu ikut duduk menemaninya di sana. Tak lupa kubawa buku sketsa dan pensil kesayanganku. Sementara itu Bibi Elisa menikmati ketenangan senja yang terhampar di hadapannya.
“Kamu tahu Sandi? Saat tengah malam tiba, ada peri-peri sawah bermunculan di sini,” ujar Bibi Elisa memecah keheningan di antara kami.
“Apa, Bi? Peri sawah?” tanyaku mencoba mengklarifikasi kalimat yang baru saja diucapkannya.
“Iya. Peri sawah. Peri-peri itu bermunculan dari celah-celah daun dan pepohonan yang ada di sekitar sini. Mereka beterbangan di atas tanaman. Seperti Tuhan kecil mereka menyebar cahaya-cahaya indah kepada bunga-bunga padi yang masih menguncup,” lanjut Bibi Elisa.
“Ah! Bibi pasti bercanda. Mana ada peri sawah. Mungkin yang Bibi lihat kunang-kunang di malam hari,” sahutku ringan.
Bibi Elisa tertawa ringan seraya berkata, “Kalau kamu ragu. Cobalah buktikan sendiri.”
Mendengar ucapan Bibi Elisa, rasa penasaranku bertambah berkali lipat. Rasa-rasanya aku ingin membuktikan kebenaran ucapan Bibi Elisa. Di samping itu, aku juga ragu. Jangan-jangan Bibi Elisa hanya ingin mengelabuiku saja. Sebagai penulis cerita fiksi fantasi, imajinasi Bibi Elisa tak bisa dianggap remeh. Bisa jadi aku akan menjadi korban dari imajinasi fiksi fantasinya.
Meski begitu, langkahku sudah tiba di gubuk sawah saat menjelang tengah malam. Rasa penasaranku tak bisa dibendung lagi. Aku tak lagi peduli jika pada akhirnya Bibi Elisa akan menertawakanku saat tahu aku begadang semalaman di sawah untuk membuktikan kebenaran ceritanya.
Diam-diam aku duduk di atas gubuk tua favorit Bibi Elisa. Seperti orang konyol aku berjaga hingga pukul 12 malam. Suara jangkrik mengerik semakin nyaring. Meski tak pernah kursus tarik suara, erikan nyaringnya cukup merdu untuk didengarkan.
Tiga puluh menit pun berlalu. Tak ada satu pun tanda-tanda kejanggalan tertangkap oleh dua bola mataku. Hatiku mulai mendengus kesal. Bibi Elisa benar-benar menipuku!
Kesal, aku pun turun ke bawah. Aku tak mau begadang semalaman di tengah sawah. Lebih baik tidur di dangau halaman depan Bibi Elisa. Paling tidak ikan-ikan nila kesayangannya jauh lebih bersahabat dibanding ular sawah yang bisa datang kapan saja.
Baru beberapa langkah aku meninggalkan gubuk, cahaya-cahaya terang bermunculan dari balik dedaunan. Semakin lama cahaya itu semakin terang. Layaknya lampu sorot dalam pertunjukan teater.
Makhluk-makhluk kecil itu bermekaran dari dalam tubuh sorotan cahaya. Bentuk tubuhnya seperti manusia. Hanya saja daun telinga mereka lancip. Benar-benar mirip Tinkerbell dalam film Peterpan.
Mereka beterbangan kesana kemari. Langkah-langkah mungilnya beriak riang menyusuri tanaman padi hijau di sawah. Sama persis dengan ucapan Bibi Elisa, peri-peri sawah itu menyebarkan cahaya-cahaya ke bunga-bunga padi yang sedang menguncup. Perlahan kuncupan bunga padi berkembang.
Tak pernah sekalipun aku melihat bunga padi bermekaran. Aku tak pernah mengira akan secantik ini rupanya. Hatiku berdecak kagum mengamati para peri sawah bekerja penuh canda dan tawa. Mereka mendendangkan lagu diiringi musik orkestra angin malam.
Salah satu dari mereka terbang mendekatiku. Bola mataku tiada mampu berpaling darinya. Peri sawah tepat berada di depan batang hidungku. Indah penuh serpihan cahaya putih.
“Kamu keponakan Bibi Elisa kan?” sapanya ramah.
“I..iya. Aku Sandi. Kata Bibi Elisa ada peri sawah di malam hari. Aku ingin melihatnya,” jawabku sekenanya. Aku tak tahu harus berkata apalagi.
Peri sawah itu tertawa seraya berkata, “Ikutlah denganku”.
Dia terbang menjauhiku. Tanpa berpikir panjang kuikuti kepakan sayapnya yang semakin lama semakin cepat. Aku terus mengejarnya hingga tiba di depan sebuah pelataran yang di tengahnya terdapat sebuah kolam berwarna keemasan.
Peri sawah itu terbang menuju tengah kolam. Di sana ada sebuah permata berwarna biru keperakan. Ukurannya hampir sama besarnya dengan tubuh peri itu. Dengan kemampuan sihirnya, peri sawah itu membawanya tepat di hadapanku.
“Aku dulu ingin memberikan ini kepada Bibimu. Sayangnya dia menolak. Katanya, ada orang lain yang lebih pantas untuk mendapatkan permata ini. Aku sering sekali melihat kalian berdua melintasi persawahan. Aku pikir orang yang dimaksud Bibimu itu adalah kamu,” jelas peri sawah itu.
“Aku? Mana mungkin. Aku tidak bisa menerima permata itu. Lagipula aku tak akan mungkin tinggal di sini,” sergahku secepatnya.
“Benarkah? Aku kira kamu akan melanjutkan usaha Bibi Elisa bertani dan membangun sekolah alam di sini.”
“Tidak. Aku tidak mungkin bisa. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan di kota,” jelasku menengarai kesalahpahaman di antara kami.
Perlahan raut wajah peri sawah itu berubah. Kesedihan tersirat jelas di wajahnya. Peri sawah itu terbang lagi ke tengah kolam. Dikembalikannya lagi permata itu ke tempat asalnya.
Keesokan paginya aku kembali ke rumah Bibi Elisa. Di depan rumah sudah tampak mobil merah kesayangan istriku terparkir dengan menawan. Aku segera bersiap dan pamit pulang.
Aktivitas rutin di kantor sudah menungguku. Tumpukan berkas perjanjian dan rencana kerja perusahaan harus segera diselesaikan. Kami bekerja berkejaran dengan waktu dari pagi hingga senja tiba.
Saat itulah aku seringkali menyengajakan diri untuk pulang dengan bersepeda. Perlahan kukayuh sepeda onthel-ku menyusuri jalanan. Deretan kendaraan bermesin itu menderu menguarkan asap dari knalpot.
Tak ada matahari senja yang dapat kutangkap. Yang ada hanyalah jajaran gedung-gedung pencakar langit. saat berhenti di lampu merah, para pengamen dan pengemis turun ke jalan. Dari satu kendaraan ke kendaraan yang lain mereka sambangi. Berharap ada sepeser uang receh yang bisa dibagi.
Entah kenapa aku merasakan ada lubang menganga di dadaku. Kutarik napasku dalam-dalam tapi rasa sesak terus saja datang. Memperbesar lubang menganga yang sudah ada. Terbersit bayangan Bibi Elisa di benakku. Kata Ayah, Bibi Elisa sudah berhenti mengajar di universitas. Dia ingin menikmati hidup di rumah pelosoknya.
Terbayang semburat senyum riang Bibi Elisa saat bersepeda berkeliling desa melewati hamparan sawah luas saat sore hari. Bayangan peri-peri sawah itupun kemudian menyergap pikiranku. Ah…!
Mira Tri Rahayu, mahasiswa Sastra Indonesia UGM 2010. Ingin segera menyelesaikan studi dan melanjutkan aktivitas berkhayal lebih intens lagi. Tanpa imajinasi, ujarnya, kita akan materi kering di tengah arus modernisasi.